OLEH: Indar Ismail Jamaluddin*
Menarik membaca pendapat Saprillah, Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Tulisan berjudul Virus Covid-19 dan Kelas Sosial tersebut pertama kali dimuat laman Balai Litbang Agama Makassar pada Sabtu, 28 Maret 2020 dan dengan cepat menyebar menyentil kondisi sosial kita saat ini.
Saya mendapati tulisan itu pada Minggu pagi, dan sekali lagi, keesokan harinya melalui grup WhatsApp kampus.
Tulisan saya kali ini bukan untuk mengulas atau memberi penilaian terhadap tulisan tersebut -tentu saja karena keterbatasan keilmuan saya. Yang justru menarik adalah ide penulis Saprillah bisa menjadi rantai solusi atas penyebaran korona atau Coronavirus Disease-19 (Covid-19) saat ini.
Saprillah menyebut, social distancing yang ditawarkan kelompok kelas menengah dengan ‘mengurung diri’ di rumah sambil mencuri perhatian di media sosial bukan solusi tepat untuk memutus mata rantai penyebaran virus.
“Jika egoisme kelas masih bertahan dengan memperhatikan keselamatan sendiri, maka apa yang bisa menahan kelas bawah untuk tetap di rumah sambil menahan perut kelaparan? Jangankan untuk membeli masker dan hand sanitizer yang harganya membumbung tinggi. Membeli beras saja mereka belum tentu bisa.” Begitu satu penggalannya.
Siapa kelas menengah yang dituntut dalam tulisan ini? Marx, sebagaimana disinggung sang penulis, tidak menyebut siapa kelas menengah. Franz Magnis Suseno (2010) mengatakan, Karl Marx hanya merinci dua kelas sosial, yakni borjuis atau pemilik modal -termasuk dalam hal ini tuan tanah- serta kelas pekerja/buruh (proletar).
Relasi kedua kelas ini dibangun atas dasar produksi. Definisi mengenai kelas menengah bisa kita lihat dari klasifikasi Asian Development Bank (ADB), yakni masyarakat dengan pengeluaran rata-rata 4-20 dollar AS per hari.
Artinya, pengeluaran bulanan minimun Rp2 juta sebulan sudah bisa dikategorikan kelas menengah. Bank Dunia menyebutkan ada 52 juta penduduk kategori kelas menengah di Indonesia atau satu dari lima penduduk.
MENDENGARKAN PUBLIK
Keterlibatan publik pada semua lapisan kelas sosial dalam penanganan bencana di Indonesia -terutama bencana alam- terbukti ampuh memberi solusi bagi pemerintah, lebih-lebih lagi korban. Duka akibat gempabumi disusul tsunami, dan likuefaksi di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 misalnya, dapat dihibur oleh solidaritas nasional dan internasional.
Bahkan hingga hari ini, masih ada organisasi sosial yang menuntaskan misi kemanusiaannya, membangunkan rumah bagi korban terdampak.
Di lain pihak, mau tidak mau, lompatan teknologi memaksa pengambil kebijakan menghadapi risiko kritik. Saran dan pendapat publik menjadi lebih variatif, dari yang halus sampai yang tajam, terutama di laman-laman media sosial dan media massa.
Kita apresiatif dengan kondisi ini mengingat sudah lama menyaksikan kebijakan yang minim partisipasi publik. Kalau pun dilibatkan, ialah publik yang dianggap merepresentasi kebijakan pemerintah.
Memang benar suara rakyat seringkali disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan, namun dengan dalih anggaran terbatas, sebagian usulan itu menumpuk begitu saja di kertas laporan reses anggota DPRD. Peran publik biasanya menjadi opsi jika keadaan genting.
Simak apa yang dikatakan Menko Polhukam, Mahfud MD tempo hari. “Apabila serangan virus (Covid-19) semakin membesar, semua elemen perlu dilibatkan. Tentu kalau sudah menyangkut peran kepala daerah, RT, RW, lurah, camat dan sebagainya harus digerakkan semuanya secara simultan untuk memerangi virus ini.” (Kompas.com, 24/3/2020).
Sejatinya, good governance atau pemerintahan yang baik, menuntut partisipasi publik. Sayangnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pijakan kebijakan publik di Indonesia, hanya memberikan publik ruang sebatas keaktifannya, tanpa ruang khusus di mana mereka mengambil peran (Nugroho, 2018).
Apa yang terjadi kemudian? Implementasi sebuah kebijakan tidak akan berdampak maksimal. Donal Van Meter- Carl Van Horn (1975) jauh hari telah mengingatkan pemerintah mengenai lingkungan eksternal (aspek sosial, politik, dan ekonomi) yang sangat memengaruhi kesusksesan penerapan sebuah kebijakan.
Nugroho membantu mendefinisikan aspek sosial tersebut sebagai opini atau pendapat publik. Horton dan Hunt (1984) mengurai opini publik sebagai pandangan yang dianut sejumlah besar orang, atau pandangan yang menonjol di kalangan penduduk.
Lalu siapakah publik yang bisa memberikan pendapat dalam sebuah kebijakan? Selain representasi seperti pekerja media massa, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, budayawan, akademisi, aktivitis perempuan, organisasi non pemerintah, organisasi komunitas, juga tentu saja masyarakat sasaran kebijakan itu sendiri.
JAMINAN KELAS MENENGAH
Penyakit menular menyasar seluruh kelompok sosial, tak peduli kelas atas, menengah, atau kelas bawah. Dalam kasus Covid-19, sejauh ini identitas mereka yang diumumkan terpapar adalah kelompok kelas menengah.
Di Indonesia, mula-mula dari pekerja seni (seniman dansa), lalu tenaga kesehatan yang kehilangan nyawa karena berupaya menyelamatkan nyawa, lalu kepala daerah dan anggota DPRD.
Di luar negeri ada pangeran, perdana menteri, wakil presiden, menteri, sampai olahragawan, dan artis papan atas. Dengan alasan transparansi -atau juga untuk mengundang simpati- mereka rela membagikan kabar tersebut ke publik.
Alat pendeteksi cepat (rapid test) juga pertama-tama diberikan pemerintah pusat untuk mereka yang rentan terpapar, terutama yang baru datang dari luar negeri atau belum lama mengunjungi daerah penyebaran virus di dalam negeri.
Dalam kasus ekstrem atau mengalami force majeur, kelas menengah atau mereka yang merangkak menuju kelas atas, hidup dengan berdiam diri di rumah masih bisa tersambung dari saham yang berputar, tabungan, atau upah tetap bulanan -untuk faktor terakhir, sepanjang negara belum bangkrut.
Tapi mari membayangkan mereka bekerja di sektor swasta: karyawan barang dan jasa yang gajinya mengandalkan kontribusi pelanggan. Jika pelanggan mogok membeli, seperti saat ini, darimana perusahaan mampu membiayai keluarga mereka?
Atau dari sebagian besar rakyat yang bergantung pada rezeki harian, yakni sektor informal dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terganggu selama masa tanggap darurat Covid-19.
Sebut saja pengojek offline, tukang sol sepatu, penjual pisang goreng bermodal satu sisir setiap hari, penjual ember keliling, penjual jamu gendong, penambal ban, tukang parkir, dan tukang pewarna baju keliling, dan sektor UMKM lainnya. Atau tukang pengumpul pasir yang mengambil risiko menyelam di sungai, pembuat batu bata, buruh bangunan, pemulung, pengamen, pengemis, pedagang bakso, penjual sayur dan ikan skala kecil, pekerja seks komersial, serta aktivitas apapun yang terkait hiburan, jasa keamanan, dan pariwisata. Termasuk dalam hal ini adalah penghuni panti sosial, kelompok disabilitas, pegawai rumah ibadah, dan pekerja sosial yang selama ini bergantung pada kedermawanan donatur, serta honorer daerah dengan penghasilan tak seberapa. Pikirkankanlah nasib hidupnya jika berdiam saja di rumah?
Demikian halnya tenaga medis yang berstatus honorer dan kontrak yang melawan maut dan meninggalkan keluarganya di rumah.
Pemerintah sebenarnya telah memikirkan opsi memberikan jaminan hidup (jadup) selama masa penanggulangan Covid-19. Ada kartu sembako dan prakerja, jaminan ketersedian logistik, pengurangan pembayaran listrik (selama tiga bulan), dan relaksasi kredit.
Untuk membantu jadup, pemerintah pusat tidak akan mungkin mampu menanggung semuanya, karena itu butuh dukungan pemda agar bisa mengatasi masalah ini.
Kendalanya, kemampuan fiskal setiap daerah berbeda. Kita tahu, anggaran sudah dikunci dan baru bisa dirubah di akhir tahun. Karenanya, salah satu kontribusi yang bisa dilakukan saat ini adalah mengundang kesadaran kelas menengah ke atas untuk ikut peduli dengan kelas bawah, rakyat kecil.
Hal yang kita syukuri adalah kesadaran kelas menengah-atas yang lahir sejak awal kemunculan virus. Yang menonjol adalah partisipasi untuk memberikan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker atau pakaian khusus untuk pekerja rentan, dan juga untuk publik secara umum.
Para penghibur dan pekerja seni papan atas menyumbangkan sebagian penghasilannya. Anggota dewan dengan pengawalan pers di daerah, juga turun langsung membagi-bagikan masker. Media mainstream dan pegiat media alternatif, juga membantu mengumpulkan kepedulian pembaca.
Hemat penulis, kiranya pemerintah bisa menfasilitasi partisipasi publik kelas menengah-atas yang besar ini. Untuk menguji kembali solidaritas tersebut, saran berikut bisa dilakukan di daerah.
Pertama, pemerintah daerah menetapkan kelompok sasaran penerima bantuan jaminan hidup (jadup) selama masa tanggap darurat Covid-19. Pemda mendata relawan berintegritas yang siap mengumpul dan mendistribusikan bantuan dan titik-titik penerima secara akurat.
Kata kuncinya adalah data sasaran. Mekanisme distribusi perlu diatur sedemikian rupa untuk menghindari gejolak sosial. Misalnya, pemerintah menyiapkan nomor-nomor kontak penyalur bantuan (bantuan bisa dijemput) atau menyediakan nomor rekening donasi.
Dengan kontrol institusi pemda, relawan selanjutnya menggunakan dana dari donatur untuk membeli kebutuhan penerima jadup. Setiap waktu nilai bantuan dan bantuan yang telah diserahkan dilaporkan ke publik.
Untuk transparansi, pemda bisa menggandeng media massa dan akuntan publik. Sumber bantuan lain adalah cadangan pangan yang dialokasikan pemda untuk bencana alam -atau bisa juga anggaran cadangan bencana pemerintah desa.
Penulis menyarankan pemerintah tidak mengambil alih distribusi bantuan guna menghindari beban pekerjaan dan penyalahgunaan bantuan. Mekanisme ini akan berhasil jika terjadi kerja sama yang baik antara relawan dan rukun tetangga (RT).
Jika wilayahnya padat penduduk, ketua RT bisa mengurai keluarga sasaran bantuan dalam kelompok-kelompok. Contohnya, sepuluh keluarga dikontrol oleh satu orang wakil RT. Bantuan jadup harus diantarkan langsung ke rumah guna menghindari keramaian.
Kedua, pemda mendata para pendonor. Mereka adalah pejabat pemerintah, pelaku usaha, dan kelompok menengah lainnya. Tapi, semua ini harus dimulai dari kepala daerah-wakil kepala daerah, sekretaris daerah, dan para kepala dinas dan keluarganya serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, seperti kejaksaan, kepolisian, hakim, dan pimpinan perguruan tinggi dan koleganya. Termasuk dalam hal ini pemilik media, perancang anggaran (DPRD), dan pelaksana anggaran (pekerja proyek skala miliar). Para pejabat pemerintah bisa mengikhlaskan sebagian penghasilan bulanannya selama masa tanggap darurat.
Ketiga, pemda harus memastikan pasokan barang kebutuhan pokok (makanan, minuman, APD masker, sabun, desinfektan, serta bahan bakar gas) ke daerah berlangsung normal, sekaligus menjaga agar kelompok menengah tidak melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok.
Kekhawatiran penimbunan barang bisa saja terjadi, karena kebutuhan untuk mengamankan stok makanan, minuman, masker, antiseptik, dan gas diikuti dengan datangnya Ramadan. Sehingga bisa dikatakan kebutuhan pokok akan menjadi dua kali lipat daripada sebelum Ramadan.
Untuk memaksimalkan kebijakan ini, dibutuhkan kerja sama dengan pelaku usaha untuk mengontrol nilai pembelian barang setiap orang. Sembari itu, aparat penegak hukum harus tegas terhadap mafia yang memainkan harga barang selama masa tanggap darurat Covid-19.
Kelangkaan barang di pasaran, terutama makanan, APD masker, desinfektan, dan gas, sementara kebutuhannya saat ini sangat tinggi, akan menyebabkan gejolak sosial sekaligus mempercepat risiko penularan virus. Masyarakat akan keluar rumah mencari kios, toko atau apotik, bahkan kalau stok habis tidak menutup kemungkinan akan terjadi tindak kriminal pencurian dan penjarahan.
Keempat, pemda harus memanfaatkan armada sumber daya yang melimpah di daerah. Kampus dengan segala kepemilikan ahli taktis kelas menengahnya seperti dosen ilmu kesehatan, pemerintahan, kebijakan publik, sosiologi, antropologi, komunikasi, teknik, biologi, kimia, fisika, pertanian, manajemen, ekonomi, hukum, dan sebagainya, ditambah mahasiswanya, bisa memberikan sumbang saran dan tenaga dalam menangkap tantangan kondisi di daerah.
Demikian halnya organisasi sosial non pemerintah-pegiat sosial kemanusiaan, kerja-kerja lapangan mereka selama ini dapat dipinjam untuk membantu pemerintah menemukan formula yang tepat dalam mencegah penularan Covid-19 di daerah. Tokoh budaya/kepala suku/ikatan kerukunan, tokoh agama atau pemimpin organisasi keagamaan, juga wajib dirangkul dan dimintai pendapatnya mengenai model komunikasi efektif kepada publik selama masa tanggap Covid-19.
SEMOGA HANYA SEKALI
Beberapa hari lalu, seorang teman sekolah menyarankan agar momen reuni yang sudah lama direncanakan diganti dengan membantu orang-orang terdekat. Yakni mereka yang tidak dapat bekerja lagi karena virus.
Hal yang membuat saya tergugah adalah kalimat terakhir dia: kita masih dapat melaksanakan reuni berkali-kali, tapi melawan virus ini cuma sekali kesempatan.
Tentu saja solidaritas untuk membantu sesama selama tanggap darurat Covid-19 sangat masuk akal dan relevan dilaksanakan. Sementara karantina wilayah sepertinya sulit terwujud mengingat beban pemerintah (pusat) yang terlanjur berat.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyebut tanggung jawab yang besar bagi pemerintah pusat jika karantina wilayah menjadi opsi saat ini. Pasalnya, selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam pelaksanannya, pemerintah pusat baru melibatkan Pemda dan pihak terkait.
Di India, kebijakan karantina wilayah diikuti gejolak sosial karena minimnya dukungan kompensasi. Kita tentu tidak mau seperti India. Karenanya, menjaga sinergitas kehidupan antarkelas sosial adalah kunci untuk melewati badai Covid-19 hari ini.
*Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Publik







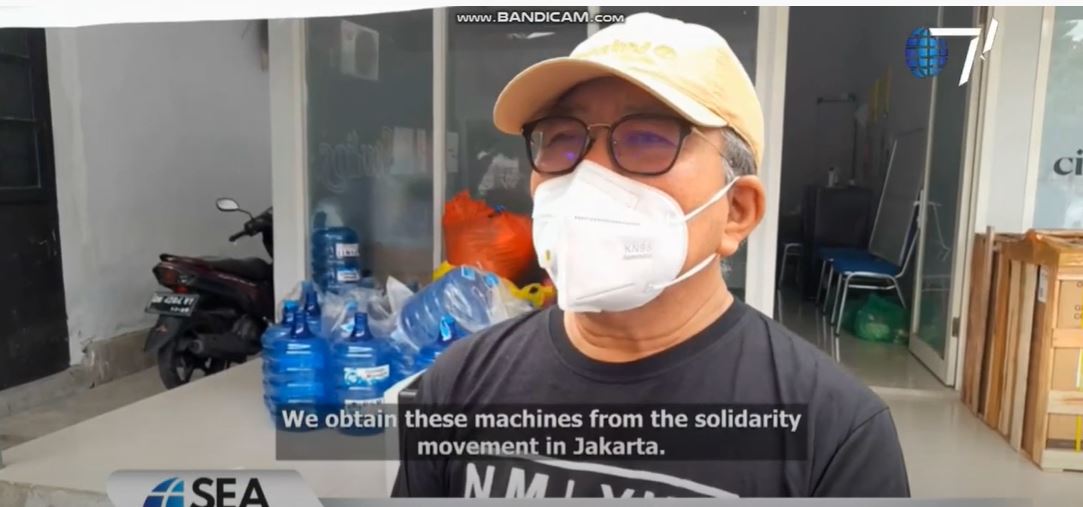






Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.