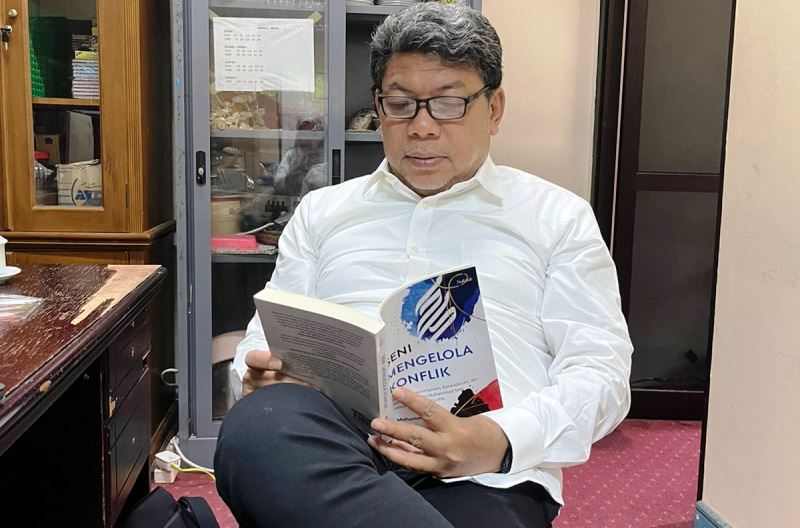PALU – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah (Sulteng) menilai Badan Bank Tanah (BBT) telah abai terhadap penghormatan masyarakat hukum adat (MHA) dan menyimpang dari prinsip reforma agraria sejati.
Kritik tersebut disampaikan menyusul sosialisasi BBT yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (26/09) lalu.
Manager Kajian, Analisis, dan Pendampingan Hukum WALHI Sulteng, Sandy Prasetya Makal, mengatakan, paparan BBT lebih menekankan paradigma penguasaan tanah untuk investasi dan proyek strategis nasional, alih-alih mengedepankan pemulihan ketimpangan agraria sebagaimana mandat utama reforma agraria.
“Masyarakat masih ditempatkan sebagai objek perampasan tanah yang timpang dan tidak berkeadilan, bukan sebagai subjek yang berperan dalam kebijakan agraria atas tanahnya sendiri,” tegasnya.
Dalam presentasinya, BBT mengklaim telah menguasai sekitar 7.123 hektar lahan melalui Hak Pengelolaan (HPL) yang tersebar di Kabupaten Poso seluas 6.648 hektar, di Kabupaten Sigi 160 hektar, dan di Kabupaten Parigi Moutong 315 hektar.
Wilayah tersebut mencakup desa-desa adat dan penggarap seperti Alitupu, Maholo, Winowanga, Kalemago, dan Watutau.
Namun, menurut WALHI, klaim tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa mekanisme partisipatif yang seharusnya melibatkan masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah.
WALHI menilai praktik BBT berpotensi mengaburkan mandat reforma agraria. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 secara jelas menekankan fungsi sosial tanah dan kewajiban negara mencegah penumpukan penguasaan lahan.
Namun, rencana pemanfaatan yang dipaparkan BBT justru lebih banyak dialokasikan kepada investor besar seperti TH Group Vietnam seluas 3.500 hektar, Universitas Hasanuddin 1.000 hektar, serta proyek militer dan resort pariwisata.
Arah kebijakan tersebut dinilai menggeser prioritas utama reforma agraria yang semestinya memberikan tanah kepada petani, masyarakat adat, dan penggarap yang telah lama memanfaatkan lahan.
Kritik lain yang disampaikan adalah pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat, khususnya di Desa Watutau.
Kronologi yang dipaparkan BBT bahkan memasukkan proses kriminalisasi warga yang mencabut patok dan plang di atas tanah yang diklaim sebagai HPL, hingga penetapan mereka sebagai tersangka.
WALHI menilai pendekatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menekankan penyelesaian konflik melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), mediasi, konsultasi, dan koordinasi, bukan dengan kriminalisasi dan pendekatan represif aparat.
WALHI juga menyoroti minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan masterplan pemanfaatan lahan.
Padahal, Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 mewajibkan adanya inventarisasi dan identifikasi yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Petunjuk teknis BPN tahun 2024 bahkan menekankan perlunya pemetaan sosial melalui wawancara, validasi, dan musyawarah. Namun, dalam materi yang dipaparkan BBT, tidak ada penjelasan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut.
Selain aspek sosial, WALHI memperingatkan adanya ancaman serius terhadap lingkungan.
Target BBT untuk memperluas penguasaan lahan hingga ratusan ribu hektar di berbagai kabupaten seperti Banggai, Morowali Utara, dan Parigi Moutong dikhawatirkan memicu deforestasi, alih fungsi lahan pertanian, hilangnya ruang hidup satwa, serta menimbulkan konflik sosial-ekologis baru.
Kondisi ini, menurut WALHI, bertentangan dengan amanat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pemerintah memperhitungkan daya dukung lingkungan sebelum menetapkan kebijakan pemanfaatan ruang.
Lebih jauh, WALHI menilai status BBT sebagai badan sui generis berpotensi melahirkan sentralisasi penguasaan tanah di tangan negara.
Sentralisasi ini membuka peluang komersialisasi lahan secara masif, mempersempit ruang hidup masyarakat, dan berlawanan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
WALHI mencontohkan, sejak penetapan tanah eks-HGU sebagai aset BBT, warga di sejumlah daerah menghadapi pemasangan patok dan plang tanpa persetujuan mereka, bahkan di beberapa lokasi ditandai sebagai area latihan Brimob, yang justru menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat.
Atas dasar itu, WALHI Sulawesi Tengah mendesak Gubernur Sulteng memastikan BBT benar-benar menjalankan mandat reforma agraria sejati, bukan sekadar menyiapkan lahan untuk investasi.
WALHI juga meminta BBT menghentikan praktik kriminalisasi terhadap masyarakat adat, membuka ruang dialog setara dengan GTRA, serta menjamin alokasi minimal 30 persen lahan diberikan kepada petani penggarap.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN diminta melakukan audit sosial dan lingkungan sebelum memutuskan pemanfaatan lahan, serta memastikan agar masyarakat menjadi subjek utama dalam penetapan kebijakan agraria.
“Reforma agraria sejati adalah mandat konstitusi, bukan proyek administrasi. Redistribusi tanah harus berpihak pada rakyat kecil dan memperbaiki ketimpangan struktural, bukan menjadi legitimasi baru bagi ekspansi investasi skala besar yang mengorbankan ruang hidup masyarakat,” pungkas Sandy.