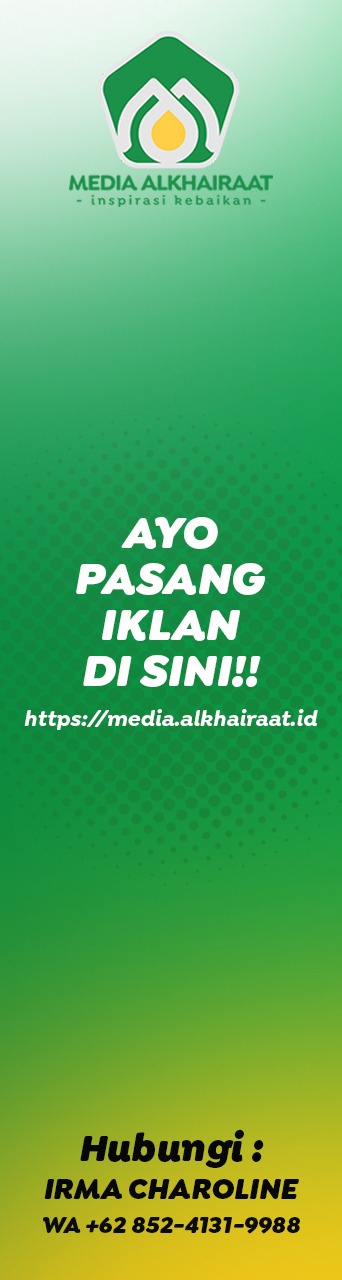OLEH: Dr. Muhammad Hatta R. T., SH. MH*
Perjuangan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, mengalami perubahan paradigma dari hukum positivis menuju hukum inklusif yang progresif, responsif dan partisipatif.
Hukum inklusif merupakan paradigma yang beranjak dari hukum positivis yang kaku menuju sistem hukum yang lebih responsif dan partisipatif, khususnya bagi kelompok marginal seperti Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Paradigma ini menempatkan pengakuan terhadap pluralisme hukum dan partisipasi aktif sebagai pilar utama dalam pencapaian keadilan substantif.
Hukum inklusif menekankan integrasi norma adat dalam sistem hukum nasional dan penghormatan atas hak-hak tradisional yang melekat secara turun-temurun, sebagai manifestasi pengakuan martabat dan identitas kolektif.
Dalam konteks Indonesia dan secara khusus Sulawesi Tengah, hukum inklusif mewajibkan negara untuk memberikan ruang partisipasi MHA dalam perencanaan, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya alam terutama hutan adat yang merupakan basis identitas sosial dan ekonomi masyarakat adat.
Landasan yuridis utama terdapat pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945, yang secara eksplisit mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012).
Dalam kerangka hukum inklusif, proses advokasi pengakuan hutan adat sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Sulawesi Tengah dipandang sebagai terobosan implementatif yang menyatukan kepentingan hukum adat dengan kebijakan tata ruang wilayah.
Hal ini menjadi langkah konkret menyelaraskan aspirasi MHA dengan kebijakan daerah sehingga hutan adat tidak sekedar ada secara sosial-kultural, tetapi juga mendapat status hukum yang melindungi dan melegitimasi eksistensinya.
Pengakuan hutan adat sebagai KSP membuktikan keberhasilan implementasi hukum inklusif dalam penataan ruang wilayah yang memperhatikan aspek sosial budaya dan keberlanjutan ekologis.
Integrasi hutan adat dalam RTRW 2023-2042 memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan kawasan, dan mencegah klaim sepihak oleh pihak lain yang berpotensi merugikan MHA. Ini juga merupakan langkah preventif yang berlaku terhadap konflik agraria dan eksklusi sosial yang kerap terjadi akibat ketidakharmonisan regulasi dan kewenangan yang kabur antara lembaga pusat dan daerah.
Meski RTRWP telah menetapkan hutan adat sebagai KSP, tantangan utama yang masih harus dihadapi adalah fragmentasi regulasi yang sering kali melemahkan perlindungan hukum terhadap MHA. Misalnya, UU Cipta Kerja yang memusatkan kewenangan dalam penataan agraria dan tata ruang nasional dapat bertentangan dengan UU Pemerintahan Daerah serta semangat pengakuan hak adat.
Ketidakselarasan ini menimbulkan ambiguitas hukum yang berdampak pada ketidakpastian perlindungan hutan adat dan tanah masyarakat adat, seperti yang terjadi pada kasus sengketa TORA di Kabupaten Sigi.
Kerangka hukum inklusif menuntut harmonisasi regulasi yang menjamin pengakuan hak-hak tradisional tidak dikerdilkan melalui kebijakan sentralistik, dan sebaliknya memperkuat pemberdayaan daerah dan MHA sebagai aktor utama dalam pengelolaan wilayah adat.
Advokasi pengakuan hutan adat dalam RTRWP Sulteng yang dipelopori oleh KARAMHA yang terdiri dari sembilan organisasi masyarakat sipil, yakni Yayasan Merah Putih (YMP) Sulteng, Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Sulteng, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulteng, dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulteng.
Selanjutnya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulteng, Perkumpulan Bantaya, Perkumpulan HuMa Indonesia, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), serta peran kampus melalui Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako (Untad).
Hal ini mencerminkan komitmen kolektif terhadap inklusivitas hukum, serta menghadirkan contoh ideal perjuangan hukum inklusif di Indonesia.
Sejak 2018, melalui strategi berlapis meliputi advokasi kebijakan berbasis bukti, dialog multi-level, dan mobilisasi publik, koalisi ini berhasil mendorong DPRD dan pemerintah provinsi mengakomodasi enam hutan adat seluas 17.501 hektar sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
Enam hutan adat yang diakui sebagai KSP adalah Wana Posangke (Morowali Utara), Marena, Huakaa Topo Ada To Masewo, Moa, Suaka Katuwua To Lindu, dan Ngata Toro (Kabupaten Sigi).
Pengakuan ini tidak hanya memberikan status hukum yang mengikat, tetapi juga mengukuhkan hak-hak sosial budaya masyarakat adat serta memberikan dasar perlindungan wilayah adat dari intervensi sepihak pihak ketiga atau korporasi.