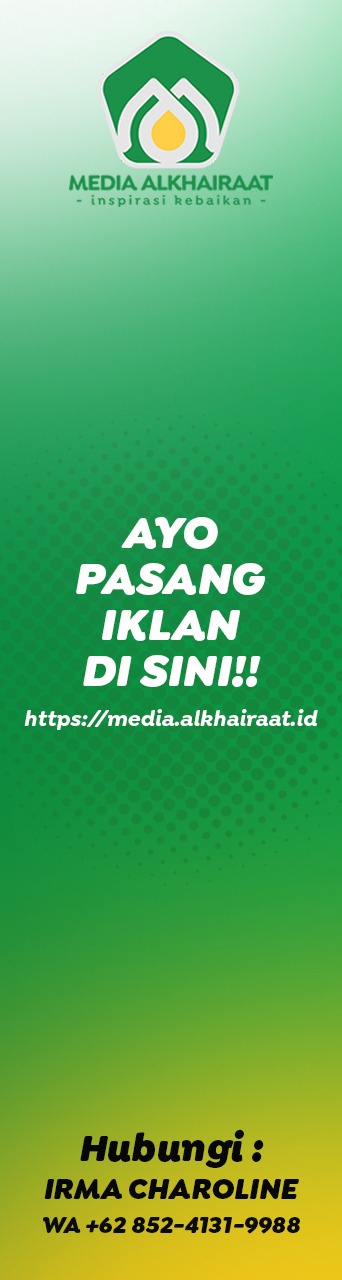OLEH: Rusdin*
Menelaah Dinamika Hubungan Islam-Barat di Era Polarisasi Global
Ketika asap hitam membumbung dari reruntuhan Gaza, sementara di sudut lain dunia, demonstran memenuhi jalan-jalan Paris dan London, kita menyaksikan babak terbaru dalam saga panjang hubungan Islam dan Barat.
Kisah ini, dengan segala kompleksitasnya, telah berlangsung selama berabad-abad yang ditenun dari benang-benang sejarah, geopolitik, dan identitas yang saling berkelindan.
Saya teringat dengan makalah yang pernah saya tulis “Islam dan Barat: memahami perbedaan dan persamaan Ideologi” seolah menjadi cermin yang memantulkan bayangan masa lalu sekaligus memproyeksikan bayangan masa depan dari hubungan kedua peradaban ini.
Geografi Konflik yang Terus Bergeser
Di tengah lanskap global yang memanas, kita menyaksikan bagaimana “kesenjangan geografis” yang diidentifikasi dalam paper tersebut terus bermetamorfosis.
Apa yang dulu merupakan batas fisik antara “Dar al-Islam” dan “Dar al-Harb” kini telah berubah menjadi batas-batas digital yang menembus dinding-dinding kota dan negara.
Saat ini, di Eropa Barat, minoritas Muslim yang semakin bertambah dan hampir mencapai lebih dari 25 juta jiwa. Jumlah populasi tersebut, telah menciptakan geografi baru yang kompleks.
Kemudian, di Perancis, negara dengan populasi Muslim terbesar di Eropa, pemandangan masjid berdiri berdampingan dengan katedral historis bukan lagi pemandangan langka.
Namun, ketika konflik Israel dan Palestina memanas pada Oktober 2023, kota-kota seperti Paris dan Marseille menjadi panggung demonstrasi besar-besaran, menunjukkan bagaimana geografi konflik Timur Tengah kini telah bermigrasi ke jantung Eropa.
Di Amerika Serikat, komunitas Muslim yang terus berkembang lebih dari 3,5 juta jiwa. Pertumbuhan populasi tersebut, juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Saat pemerintah Biden mengambil posisi yang kuat mendukung Israel dalam konflik terkini, Muslim Amerika menemukan diri mereka dalam dilema identitas yang menggambarkan dengan sempurna “kesenjangan geografis” kontemporer.
Mereka adalah warga Amerika sekaligus bagian dari “ummah” global, dua identitas yang sering kali ditarik ke arah berbeda oleh gravitasi politik global.
Peradaban yang Terluka, Sebuah Narasi yang Terbelah
“Kesenjangan peradaban” yang diuraikan dalam makalah di atas, menemukan ekspresi dalam pertarungan narasi yang semakin intens di era digital. Ketika gambar-gambar korban sipil di jalur Gaza viral di media sosial, sementara berita tentang sandera Israel yang disiksa Hamas mendominasi headline utama, kita menyaksikan bagaimana sejarah peradaban diinterpretasikan secara berbeda oleh kedua pihak.
Di satu sisi, banyak pemikir Muslim melihat dukungan Barat terhadap Israel sebagai kelanjutan dari proyek kolonial, menegaskan kembali narasi “Perang Salib yang tidak pernah berakhir” yang sering disuarakan oleh kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hizbullah.
Di sisi lain, banyak pemikir Barat memandang konflik tersebut melalui lensa “pertahanan nilai-nilai demokrasi liberal” melawan apa yang mereka anggap sebagai “ekstremisme religius.”
Yang menarik, di tengah pertarungan narasi ini, muncul suara-suara baru yang mencoba menawarkan jalan tengah. Figur seperti Mustafa Akyol, penulis “Islam Without Extremes,” atau Irshad Manji dengan “The Trouble with Islam Today,” menggambarkan kompleksitas hubungan Islam-Barat kontemporer yang tidak bisa disederhanakan dalam dikotomi hitam-putih yang kaku.
Kultur yang Saling Menembus
Paradoks terbesar dari hubungan Islam-Barat kontemporer terletak pada “kesenjangan budaya” yang semakin tipis namun sekaligus semakin dalam. Di satu sisi, globalisasi telah menciptakan lanskap budaya yang semakin homogen.
Muslim di Jakarta menikmati film Marvel yang sama dengan rekan-rekan mereka di New York, sementara hidangan halal food truck menjadi pemandangan umum di kota-kota Barat.
Namun, di tengah homogenisasi budaya ini, identitas religius justru semakin menguat sebagai bentuk resistensi. Fenomena hijrah di kalangan Muslim urban atau kebangkitan konservatisme religius di berbagai penjuru dunia Islam menunjukkan bahwa semakin kuat penetrasi budaya global, semakin kuat pula respons kultural yang berakar pada identitas religius.
Dalam konteks ini, menarik untuk melihat bagaimana arsitektur Islam kontemporer. Seperti Museum of Islamic Art di Doha karya I.M. Pei, karya tersebut mencerminkan dialog budaya yang kompleks.
Bangunan tersebut menggabungkan elemen estetika Islam klasik dengan teknik dan material modern, menjadi metafora visual dari pertemuan dua peradaban yang terus berlangsung.
Agama di Era Post-Truth
Selain kesenjangan di atas, berikutnya adalah “Kesenjangan agama” yang kini harus dibaca dalam konteks era post-truth, di mana narasi religius sering dimanipulasi untuk kepentingan politik.
Ketika politisi seperti Viktor Orbán di Hongaria berbicara tentang “melindungi Eropa Kristen” dari “invasi Muslim,” atau ketika ISIS mengklaim bertindak atas nama Islam, kita menyaksikan bagaimana agama menjadi alat mobilisasi politik yang “powerful”.
Dan yang lebih memprihatinkan, algoritma media sosial semakin memperkuat polarisasi tersebut. Penelitian terbaru menunjukkan bagaimana algoritma Facebook dan YouTube cenderung mengarahkan pengguna ke konten yang semakin ekstrem, menciptakan “echo chamber” yang memperkuat prasangka dan stereotip negatif di kedua sisi.
Meskipun demikian, di tengah polarisasi ini, muncul juga inisiatif dialog antar agama yang signifikan. Dokumen “Human Fraternity for World Peace and Living Together” yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Grand Imam Ahmed el-Tayeb pada 2019 menunjukkan kemungkinan jembatan dialog yang mungkin dibangun.
Demikian pula, The Marrakesh Declaration (2016) yang ditandatangani oleh ratusan ulama Muslim mengenai perlindungan minoritas agama di negara-negara Muslim merepresentasikan langkah penting menuju rekonsiliasi.
Ekonomi Global dan Ketimpangan Struktural
Selain itu, “Kesenjangan ekonomi” dalam makalah di atas menjadi sangat relevan dalam konteks ekonomi global kontemporer. Meskipun beberapa negara Muslim seperti Qatar, UEA, dan Malaysia telah mencapai kemakmuran ekonomi yang signifikan, ketimpangan struktural dalam sistem ekonomi global tetap menjadi isu sentral.
Kontrol atas sumber daya energi tetap menjadi titik penting dalam dinamika Islam-Barat. Ketika negara-negara Teluk kini menggunakan kekayaan minyak mereka untuk berinvestasi dalam teknologi masa depan seperti energi terbarukan. Contohnya Masdar City di Abu Dhabi, kita dapat menyaksikan pergeseran penting dalam hubungan ekonomi global.
Yang lebih menarik lagi adalah pertumbuhan keuangan Islam (Islamic finance) sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis konvensional.
Dengan aset global mencapai lebih dari $2 triliun, keuangan Islam tidak lagi merupakan fenomena pinggiran, melainkan telah menjadi bagian integral dari lanskap keuangan global. Bank-bank besar Barat seperti HSBC dan Standard Chartered kini memiliki divisi perbankan syariah, menunjukkan bagaimana kesenjangan ekonomi kini berubah menjadi zona pertemuan yang produktif.
Ideologi dalam Dunia Multipolar
Kesenjangan terakhir dari makalah di atas adalah “Kesenjangan ideologi” yang harus dibaca dalam konteks dunia multipolar yang semakin kompleks.
Jika sebelumnya narasi dominan adalah pertentangan antara “liberalisme Barat” dan “tradisionalisme Islam,” kini kita menyaksikan munculnya berbagai varian ideologis di kedua sisi.
Dalam dunia Islam, kita menyaksikan spektrum yang luas dari Islamic democracy yang dianut oleh salah satu partai di Turki yaitu Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Islamic socialism yang diperjuangkan oleh beberapa kelompok di Timur Tengah, hingga Islamisme transnasional yang dipromosikan oleh kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir.
Demikian pula, di Barat, liberalisme klasik kini bersaing dengan populisme kanan, sosialisme progresif, dan berbagai ideologi hibrid lainnya.
Yang menarik, kita juga menyaksikan perkembangan ideologi-ideologi hibrid yang mencoba menjembatani kesenjangan ini. Pemikir seperti Tariq Ramadan dengan konsep “European Islam”-nya atau Abdullahi An-Na’im dengan visi “Islamic secularism”-nya menunjukkan bahwa dialog ideologis terus berlangsung, meskipun di tengah polarisasi yang intens.
Jembatan di Atas Jurang yang Menganga
Di tengah kesenjangan yang terus melebar, persamaan-persamaan ideologis yang diidentifikasi dalam paper di atas, yaitu demokrasi, HAM, hukum internasional, pluralisme, dan penolakan terhadap terorisme yang berpotensi menawarkan harapan bagi dialog yang konstruktif.
Kita menyaksikan bagaimana demokrasi kini ditafsirkan dengan berbagai cara di dunia Muslim mulai dari model Turki yang semakin otoriter di bawah Erdogan hingga eksperimen demokratis Tunisia yang rapuh namun bertahan.
Demikian pula, di Barat, demokrasi liberal kini menghadapi tantangan internal yang signifikan, dari populisme hingga polarisasi ekstrem.
Dalam konteks HAM, kita menyaksikan bagaimana Muslim dan non-Muslim di berbagai belahan dunia bersatu dalam solidaritas terhadap penderitaan di Gaza, menunjukkan bahwa kemanusiaan bisa menjadi landasan bersama yang mengatasi perbedaan identitas religius.
Pada saat yang sama, isu-isu seperti kebebasan beragama dan hak-hak LGBT tetap menjadi titik fiksi signifikan.
Masa Depan yang Belum Tertulis
Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, makalah “Islam dan Barat” mengingatkan kita bahwa hubungan antara kedua peradaban ini bukanlah narasi tunggal, melainkan mozaik kompleks yang terus berubah.
Kesenjangan-kesenjangan yang diidentifikasi dalam makalah tersebut bukan takdir yang tak terelakkan, melainkan tantangan yang harus dihadapi dengan dialog dan pemahaman yang lebih mendalam.
Saat ini, ketika konflik Israel-Palestina mencapai titik kritis, ketika Islamofobia dan anti-Semitisme sama-sama meningkat, ketika populisme religius mengancam kohesi sosial di berbagai belahan dunia, penting bagi kita untuk melihat melampaui dikotomi sederhana “Islam versus Barat” dan mengakui kompleksitas hubungan yang sesungguhnya.
Sebagaimana diingatkan dalam kesimpulan makalah di atas: “Barat dan Islam hanyalah merupakan sebuah nama, nama dari sebuah simbol berada pada wilayah yang berbeda dan saling memiliki sifat dan ego yang seolah mengalahkan kemauan Tuhan.”
Di tengah dunia yang terbakar oleh konflik dan kebencian, mungkin sudah saatnya kita melihat melampaui nama-nama dan simbol-simbol tersebut, dan mengenali kemanusiaan yang telah kita bagi bersama. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran (Al-Hujurat 49:13):
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ
“Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.”
Dalam dunia yang semakin terhubung kita dapat “saling kenal-mengenal” dan “Bila ada dua kebudayaan yang bertemu”, maka yang terjadi bukanlah benturan, melainkan dialog. Dan setiap dialog sejatinya, dapat membuat kedua pihak atau salah satunya “berubah”.
*Penulis adalah Dosen UIN Datokarama Palu