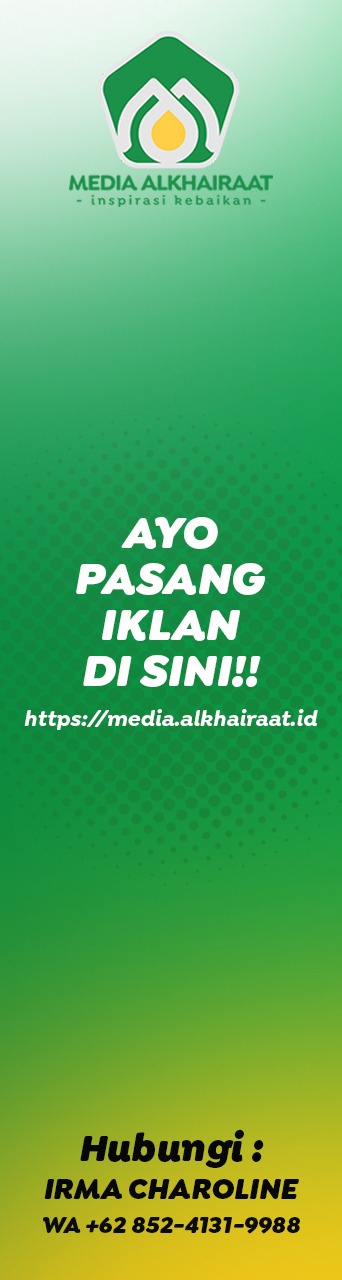PALU- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah mencatat berbagai permasalahan lingkungan dan ekologis, serta konflik lahan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sepanjang tahun 2022.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah (Sulteng) Sunardi Katili mengatakan, perkebunan skala besar, fokus melihat pada dua hal yakni Pertama, Perkebunan Kelapa Sawit dan Kedua, Kawasan Pangan Nusantara (KPN) Desa Talaga.
“Investasi Perkebunan kelapa sawit masih menyisahkan berbagai konflik rakyat 2022. Sengketa lahan berkepanjangan dengan upaya penyelesaian terkesan lambat oleh pihak pemerintah daerah masih menjadi momok bagi petani,” kata Sunardi Katili turut didampingi Ketua Dewan Daerah WALHI Sulteng Richard Labiro, di Kantor WALHI Sulteng, Jalan Tanjung Manimbaya Kota Palu, Jum’at (30/12).
Ia mengatakan, konflik lahan melahirkan gejolak protes-protes rakyat yang beberapa berujung pada kriminalisasi oleh aparat negara, mulai dari penangkapan hingga pemenjaraan terhadap petani.
Selain di sektor perkebunan kelapa sawit, WALHI Sulteng juga menyoroti salah satu Proyek Strategi Nasional (PSN) yakni Kawasan Pangan Nusantara (KPN) yang diimplementasikan di Sulteng 2022 ini.
“Penetapan KPN ini ditandatangani dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor: 504/117/.1/DBMPD-G.ST/2022 tentang Penetapan Desa Talaga Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala sebagai Kawasan Pangan Nusantara (KPN) Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional atau Food Estate (FE) seluas 1.123,59 hektar,”paparnya.
Lebih lanjut ungkapnya, hasil investigasi lapangan Yayasan Ekologi Nusantara Lestari (EKONESIA) bersama dengan Eksekutif Daerah WALHI Sulteng, September 2022, ditemukan fakta-fakta lapangan antara lain, masyarakat sekitar lokasi titik nol tak mendapatkan informasi utuh terkait rencana pembangunan KPN.
“Padahal mereka paling terdampak secara langsung dari kehadiran KPN tersebut,” urainya.
Dia menguraikan, masyarakat sekitar lokasi titik nol KPN, tidak mengetahui jenis komoditi dikembangkan di areal KPN Talaga, serta merisaukan dampak pembukaan areal KPN sebab ada sejumlah tanaman kelapa masyarakat tertebang, dan belum ada kejelasan ganti rugi tanamannya.
“Lokasi KPN berada jauh dari sumber air, dengan kebutuhan optimalisasi komoditas ditanam di lokasi itu, maka ia memerlukan sumber air dalam jumlah banyak, sehingga berpotensi memicu konflik sumber air di desa tersebut,” urainya.
Data temuan lapangan ini, kemudian menurutnya, dikonfirmasi ke pihak pemerintah melalui pertemuan pada akhir oktober 2022 dihadiri oleh Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah (Ridha Saleh).
Dalam pertemuan tersebut terungkap antara lain, ungkapnya, sosialisasi ke masyarakat setempat tidak meluas hingga seluruh lapisan masyarakat. Lokasi KPN telah di buka mencapai 10 Hektar untuk Jalan utama namun belum memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk penebangan kayu.
“Belum adanya kepastian komoditi yang akan dikembangkan dan tenaga kerja yang akan dilibatkan. Dan belum ada dokumen rencana induk, rencana kerja tahunan, UKL/UPL sebagai rujukan,”tuturnya.
Ia mengatakan, belum ada kelembangaan pelaksana dan skema pengelolaannya (BUMD atau Investor luar) serta pola pelibatan masyarakat setempat .Secara eksisting Desa Talaga merupakan bagian tak terpisahkan dari Danau Talaga.
Dalam Peta Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Danau Talaga dikategorikan sebagai kawasan lindung. Hal tersebut didasari pada penetapan Kesatuan Pengelolan Hutan (KPH) Dampelas Tinombo seluas 100.912 hektar, yang ditetapkan oleh Kementrian Kehutanan 2009.
“Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 792/Menhut-II/2009 pada 2009 silam, Danau Talaga dan ekosistem sekitarnya ditetapkan sebagai bagian dari kawasan KPH Dampelas Tinombo,” katanya.
Sehingga keberadaan KPN di Desa Talaga yang bertujuan untuk menjadi lumbung pangan bagi daerah maupun Ibukota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur, diharapkan mempertimbangkan berbagai risiko-risiko dan dampak sosial serta dampak lingkungan di kemudian hari. Termasuk mempertimbangkan bahwa Desa Talaga yang berada di pesisir wilayah pantai barat Donggala, merupakan perlintasan dari Sesar Palu Koro sangat aktif, sewaktu-waktu dapat terjadi siklus gempa bumi.
“Perspektif kebencanaan menjadi urgent dalam setiap pembangunan direncanakan di Sulawesi Tengah. Tak kalah penting, ialah menimbang siapa sesungguhnya penerima manfaat ekonomi dari keberadaan KPN di Desa Talaga,”sebutnya.
Sektor Pertambangan dan Energi
Ia mengatakan, Indonesia sejauh ini merupakan pemasok terbesar, memenuhi 19 persen dari permintaan dunia akan bijih nikel. Untuk memenuhi permintaan dunia tersebut, Presiden Jokowi meresmikan smelter PT. Gunbuster Nickel Industry (PT. GNI) pada akhir 202.
Salah satu smelter terbesar yang berada di kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Dengan total nilai investasi sekitar Rp42,9 Triliun, GNI secara keseluruhan akan mengoperasikan 24-line smelter, yang mengadopsi teknologi Rotary Kiln Electric Furnace.
“Smelter GNI akan mengolah raw material yaitu bijih nikel menjadi feronikel dengan kadar 10-12 persen, dengan kapasitas produksi sebesar 1.800.000 ton feronikel per tahun, yang membutuhkan suplai/konsumsi bijih nikel sebesar 21.600.000 WMT per tahun,”ucapnya.
Masifnya investasi di sektor pertambangan nikel di Sulteng tidak hanya berhenti sampai di situ, kata dia, sepanjang perjalanan 1 semester 2022 (Januari – Juni) tercatat bahwa Sulteng menyumbang 16,2 persen dari total investasi Penanaman Modal Asing (PMA) atau sebesar 3,5 USD tingkat nasional.
“Hingga oktober ditahun ini Gubernur Sulteng Rusdy Mastura menerima “Penghargaan Layanan Investasi Terbaik II Kategori Provinsi” dari Kementerian Investasi dan BKPM,”katanya.
Degradasi Lingkungan Hidup dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Pada rangkaian kerja-kerja advokasi dilakukan 2022 oleh WALHI Sulteng menyoroti masalah-masalah ditimbulkan sejumlah aktifitas pertambangan nikel mulai dari masalah penurunan atau Degradasi Lingkungan Hidup maupun Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Aktifitas perusahaan eksploitasi pengerukan bahan baku melalui sejumlah IUP serta pembangunan Pabrik Smelter berada pada Kawasan Hutan dan Area Penggunaan Lain (APL) telah mengakibatkan beberapa masalah antara lain krisis air bersih dan banjir bandang terhadap masyarakat yang tinggal diwilayah lingkar pertambangan.
“Dengan adanya aktifitas ini terlihat jelas bahwa terjadi penurunan atau degradasi kualitas lingkungan pada 2022,”katanya.
Seperti halnya kata dia lagi, perluasan kawasan industri PT Stardust, mengharuskan perusahaan membongkar hutan dan bukit menggunakan bulldozer atau eksavator dan dinamit untuk meratakan tanah agar bisa mendirikan pabrik-pabrik di kawasan industri.
Di Kecamatan Petasia Timur dan Petasia Kabupaten Morowali Utara, terdapat kawasan hutan. Berdasarkan data berhasil diperoleh dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu. Di tempat konsentrasi pembangunan industri PT Stardust terdapat Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas.
“Untuk Kawasan Hutan Lindung luasanya 3.129,54 hektar dan Hutan Produksi Tetap 5.201,11 hektar,”ucapnya.
Di wilayah pesisir, PT Stardust mereklamasi pantai seluas 15 hektar dan akan bertambah lagi sesuai rencana proyek. Tujuannya, untuk melancarkan aktivitas bongkar muat batu bara, baja nikel dan kebutuhan lainya ke perusahaan lain. Maka dari itu, wilayah pesisir tidak luput dari eksploitasi perusahaan.
Selain itu, menurutnya lagi, masalah lain ditimbulkan dari aktifitas pertambangan nikel yakni merampas dan melanggar HAM masyarakat bermukim disekitaran pertambangan dan Buruh Pabrik.
Deretan masalah mulai dari penggusuran paksa lahan masyarakat seperti dirasakan oleh masyarakat Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Morowali oleh PT. BTIIG dan perampasan ruang tangkap nelayan diwilayah pesisir oleh PT. GNI, hingga pada masalah minimnya jaminan keselamatan dan kesejahteraan Buruh Pabrik terjadi 2022 ini.
Isu Energi Bersih
“Kita tahu sekarang global mendesak, mengajak, men-support ke semua negara untuk menggeser pemakaian energi fosil untuk semuanya masuk ke energi hijau” Joko Widodo (Presiden RI)
Di tahun 2022 ini, Pemerintah Indonesia gencar mengkampanyekan isu perubahan iklim yang diakibatkan konsumsi energi fosil (batu bara) yang massif. G20 merupakan acara akbar berkelas internasional yang menghadirkan kepala negara dari masing-masing anggotanya untuk duduk bersama membahas masalah iklim.
Maka, solusi mereka ini adalah meninggalkan energi fosil menuju energi bersih dan terbarukan.
Perusahaan yang mengeksploitasi sungai poso ialah PT Poso Energy yang merupakan bagian dari Kalla Group.
Perusahaan energi ini, kata dia, memproyeksikan 3 bendungan atau biasa disebut Poso 1, Poso 2, dan Poso 3. Istilah ini untuk proyek bendungan. Berdasarkan data dihimpun bendungan 1 menghasilkan listrik sebesar 4×30 MW, bendungan 2 menghasilkan listrik sebesar 3×65 MW+4×50 MW dan bendungan 3 akan menghasilkan energi listrik sebesar 4×100 MW.
Segala macam proyek ini mensyaratkan satu hal yaitu air (alam) sebagai modal utama (advance capital). Oleh karenanya, tidak ada modal tanpa alam yang dieksploitasi.
Yang menjadi pertentanganya, kebanyakan orang-orang menganggap PLTA (singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Air) sebagai energi bersih ini akan menjadi alternative dari energi kotor hasil pembakaran batu bara. PLTA dianggap rendah emisi, tidak polusi dan tidak menyebabkan penyakit paru. Berbeda dengan PLTU yang selalu dikritik.
Akan tetapi, kebanyakan orang lupa, bahwa bendungan yang menjadi inti dari PLTA punya cerita buruk!
PLTA Poso dan Masalah Diwariskan
Proyek Pembangunan PT. Poso Energy telah rampung dan telah diresmikan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo 2022 tepatnya februari. PLTA Poso 515 MW dibangun dalam dua tahap, PLTA Poso Eksisting dengan kapasitas 3×65 MW beroperasi sejak Desember 2012 PLTA Poso Extension dengan kapasitas 4×30 MW dan kapasitas 4×50 MW telah selesai pembangunan sejak Desember 2021.
Tapi tidak hanya itu, karena rakus air, pihak Poso Energy merubah kondisi organik Sungai Poso berdampak pada hilangnya kearifan lokal warga Tentena dan sekitarnya. Jauh-jauh hari sebelum PT Poso Energy menancapkan kuku kapitalnya di Pamona, orang Tentena dan sekitarnya sudah akrab dengan Sungai Poso dan Danau Poso.
Secara antropologis, tumbuhlah budaya beriringan dengan alam. Masyarakat disana punya tradisi turun-temurun yang disebut masango dan Waya Masapi. Ditambah lagi, jembatan tua Tentena (punya budaya historis masale sejak dulu) yang sudah menjadi simbol daerah ini sejak lama.
Apa yang menyebabkan hilangnya tradisi ini dikarenakan PT Poso Energy mengeksploitasi Sungai Poso. Aktivitas mereka antara lain mereklamasi Kompo Dongi, merekonstruksi jembatan tua Tentena atau menghilangkan dan merampas nilai budayanya, mengeruk sungai, mengeruk tebing disekitar sungai dan lain-lain.
Menurut pengakuan masyarakat sekitar danau, PT Poso Energy tidak pernah memberitahukan atau mensosialisasikan terkait adanya kegiatan uji coba pintu air bendungan. Akibatnya selama 2 tahun, petani dan masyarakat adat danau poso mengalami kerugian sangat besar. Misalnya di tahun 2020 ada sekitar 266 ha sawah dan kebun warga di 16 Desa/Kelurahaan terendam yang menyebabkan petani gagal panen sampai saat ini serta tak bisa menanam lagi, tidak cuma sampai disitu dampak dialami masyarakat sekitar danau poso juga kehilangan 94 kerbau mati akibat terendamnya 150 ha lahan penggembalaan di Desa Tokilo.
Karena gagal panen ini, banyak kepala keluarga di desa-desa seputar Danau Poso terancam miskin ekstrim yang membuat mereka mesti berhutang di koperasi dan lainya, sebagian jadi buruh harian di lahan tuan tanah.
Serangkaian upaya penyelesaian 2022 ini ditempuh oleh masyarakat dirugikan dari aktifitas PT. Poso Energy dengan sederetan tuntutannya . Mediasi berulangkali dilakukan antara warga dan pihak perusahaan difasilitasi oleh pemerintah daerah tak juga menuntaskan masalah ini. Hingga pemerintah daerah melalui Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menjanjikan untuk mempertemukan masyarakat dengan pihak perusahaan dalam hal ini Ahmad Kalla namun tidak juga terwujud.
Tambang Emas; Konflik Rakyat & Degradasi Lingkungan Hidup
Sepanjang tahun 2022, WALHI Sulteng mencatat terjadi pelanggaran disektor Pertambangan Mineral Logam Emas yang dilakukan oleh korporasi yang telah mengantongi Izin Operasi Produksi ataupun yang masih sebatas Izin Eksplorasi.
Pelanggaran-pelanggaran dilakukan berupa pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia merkuri dan sianida, beroperasinya perusahaan sebelum semua dokumen persyaratan lengkap, pelanggaran HAM dan lain-lain.
Selain melakukan pelanggaran-pelanggaran, sejak awal kehadiran korporasi-korporasi pertambangan emas sudah mendapat penolakan dari masyarakat ataupun organisasi masyarakat sipil.
Ia mengatakan, kehadiran PT. Trio Kencana di kecamatan Kasimbar, Toribulu dan Tinombo Selatan adalah salah satu contoh nyata bentuk penolakan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil 2022.
Sejak kehadiran PT. Trio Kencana 2010, telah mendapat aksi penolakan dari masyarakat di Kecamatan Tinombo Selatan (2012) dan mencapai puncak aksi penolakan pada 12 Februari 2022 oleh masyarakat di 3 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Toribulu dan Kecamatan Tinombo Selatan.
Dalam aksi penolakan kehadiran PT. Trio Kencana tersebut, 1 massa aksi atas nama Erfaldi (22 Tahun) menjadi korban peluru tajam Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 59 orang lainnya ditangkap.
Fenomena bertambah maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Emas berkedok Tambang Rakyat yang terus berlangsung selama 2022, belum secara serius ditangani oleh aparat penegak hukum, karena belum sampai menyentuh pelaku pendanaan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
Praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) kata dia, menyebabkan kerugian Negara tidak sedikit jumlahnya, kerusakan lingkungan, banjir dan rusaknya sungai-sungai sebagai sumber air minum dan sumber air pertanian masyarakat.
“Kota Palu, Kabupaten Donggala, Poso, Parigi Moutong, Tolitoli dan Buol tercatat menjadi wilayah yang subur bagi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang berkedok Tambang Rakyat tersebut,”tuturnya.
Salah satu penyebab utama carut-marut persoalan pertambangan emas saat ini adalah kata dia, karena adanya perubahan kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Logam menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, membuat kewenangan Pemerintah Daerah menjadi sangat terbatas.
Protes-protes penolakan masyarakat yang terus berlanjut terhadap kehadiran korporasi tambang emas dan juga protes masyarakat terhadap korporasi pertambangan emas yang diduga telah melakukan pelanggaran, hanya berakhir menjadi sebuah rekomendasi-rekomendasi yang tidak berujung.
Sehingga geliat sektor pertambangan dan upaya Pemda Sulteng menggenjot pendapatan daerah melalui sektor pertambangan, dan abai terhadap protes ataupun penolakan masyarakat atas kehadiran investasi tambang emas. Ini menjadi ironi ketika setiap tahunnya Pemda Sulawesi Tengah mengalami defisit anggaran rata-rata 1,65 terhadap PDRB.
Hal-hal di atas, jika tak ada penanganan serius dan fundamental oleh Pemda Sulteng dan Aparat Penegak Hukum, pada gilirannya, akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia, degradasi lingkungan hidup, turunnya populasi banyak spesies dan makin cepatnya kepunahan; pengurasan sumber daya alam, pemanasan global dan perubahan iklim.
Reporter: IKRAM
Editor: NANANG