Indonesia dianugerahi beraneka ragam budaya dan adat istiadat. Keanekaragaman inilah yang telah membesarkan Indonesia.
Kekayaan budaya ini, juga terbukti mampu menjadi filter, atas masuknya berbagai macam pengaruh buruk. Adat istiadat telah merekatkan hubungan antar manusia. Adat istiadat juga dapat diandalkan, untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan menjauhi konflik.
Sebut saja budaya Kaili. Suku asli penghuni Kota Palu, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan sekitarnya ini banyak memiliki kearifan local budaya yang masih terpelihara turun temurun.
Salah satunya adalah Tonda Talusi. Sebuah kearifan local yang memegang teguh sifat arif dan bijaksana oleh masyarakat adat lembah Palu dan lereng.
Bila dapat dimaksimalkan, maka akan memberi dampak cukup signifikan dalam menyelesaikan satu permasalahan pada komunitas masyarakat, karena saling menguatkan satu dan lainnya.
Tonda Talusi memiliki filosofi tiga buah batu penyangga, yang berarti sebuah kepemimpinan komunitas masyarakat dengan selalu berpegang pada prinsip tiga sumber hukum, yakni hukum negara, hukum adat dan hukum agama.
“Ketiganya diwujudkan dalam mekanisme pemerintahan. Adat dan agama digabung menjadi wadah penyangga berdirinya penataan masyarakat yakni pranata pemerintahan, pranata adat dan pranata agama. Ketiganya tidak boleh saling meninggalkan,” demikian disampaikan Ketua Dewan Adat I, Kecamatan Tatanga, Mohammad Nizam Rana.
Dia mengatakan, mereka akan memiliki kekuatan, kepercayaan, legalitas yang sama di dalam masyarakat. Saling menunjang. Bila salah satunya ditinggalkan, maka penyangga tersebut tidak akan seimbang.
Sehingga, kata dia, ketiganya saling menunjang dalam penerapan. Misalnya ketika ada sebuah persoalan di tengah masyarakat yang bernuansa keagamaan, maka pranata sosial di bidang keagamaanlah yang didahulukan dalam rangka menyelesaikan persoalan sesuai dengan akarnya.
“Begitupun sebaliknya. Jadi pranata mana yang didahulukan, sementara dua pranata lainnya ikut menunjang, memperkuat serta mendorong. Ketika ada persoalan di tengah-tengah masyarakat dan pranata ini saling mendukung, maka Insya Allah masyarakat bisa tertata, terkendali, tertinggi dan suasana kondusif akan tercipta,” ujar Nizam yang juga Kadis Kominfo Provinsi Sulteng itu.
Menurutnya, Tonda Talusi ini tidak hanya dimiliki Sulteng. Daerah lain pun memiliki, namun dengan sebutan berbeda, seperti Minang dimana adat bersandikan syara, syara bersandikan kitabullah.
“Mengapa di daerah lain ada. Karena dalam komunitas masyarakat, ketiga hal tersebut memang ada. Jadi Tonda Talusi ini sudah ada sejak lama, digunakan oleh orang tua kita dalam rangka menata dan memimpin masyarakat,” tambahnya.
“Saya pernah praktikkan ini saat menjadi camat di salah satu daerah di Donggala. Ketiga hal tersebut saya terapkan di tengah-tengah masyarakat. Kurang lebih lima tahun memimpin, Alhamdulilah masyarakatnya kondusif dan terkendali. Kita tidak menafikan bahwa ada juga terjadi keributan dan konflik. Tapi sifatnya temporer dan skalanya kecil dan mudah ditangani oleh tiga pranata tersebut. Semua persoalan masyarakat, baik agama, adat dan pemerintah mudah diselesaikan karena ketiganya bekerja dan saling mendukung satu dan lain,” katanya.
BUTUH POLITICAL WILL
Penegakkan adat dan tradisi di tengah-tengah masyarakat, tentunya tidak lepas dan konsistensi maupun niat baik dari pemegang kebijakan.
Satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah adanya political will dari pemegang kekuasaan/kebijakan.
“Seyogyanya jangan sampai ada ego sektoral. Apabila ada ego sektoral dalam penyelesaian suatu kasus di tengah masyarakat, maka kekuatannya tidak akan maksimal,” ujar Nizam.
Untuk itu, dia berharap kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bisa menggagas satu wadah yang didalamnya terdapat tiga pranata tersebut. Ketiga pranata tersebut tidak terstruktur, melainkan berputar sama kuat mengitari masyarakat.
“Jadi sistemnya komite atau komisioner,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Adat Kota Palu, Timudin Bouwo, mengatakan, cara menangkal tumbuhnya radikalisme dan terorisme dengan kearifan lokal adalah melalui pendekatan Tonda Talusi yang bermakna menggunakan beberapa unsur yang terlibat yaitu: tonda (tungku) pertama yang melibatkan pemerintah daerah, TNI/Polri, lalu tonda kedua melibatkan tokoh agama (toga), serta tonda ketiga melibatkan tokoh ada (toda).
Dengan pola ini, menurut Timudin, maka lebih cepat melakukan deteksi dini pada lingkungan terkecil RT, RW dan kelurahan dengan pola preemtif dan preventif karena dapat mengenal orang-orang yang berdomisili di lingkungan itu secara nama dan alamat (by name by address).
Pendekatan Tonda Talusi, menurut dia, telah digunakan dan diterapkan di Kota Palu dengan melibatkan tokoh-tokoh informal yang ada di lingkungan dan pengaruhnya sangat dihargai oleh orang banyak.
“Dan pengaruhnya sangat efektif, pelaksanaanya sudah berjalan maksimal,” katanya.
Sehingga, kata dia, tidak ada lagi masalah yang ditemui di masing-masing kelurahan, karena semua komponen melaksanakan tugas ini.
“Tonda Talusi bisa menjadi contoh daerah lain di Indonesia. Ada Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang dipimpin Lurah,” imbuhnya.
Tak hanya Tonda Talusi, suku Kaili juga memiliki kearifan lokal lain. Di Kawasan Pantai Barat, ada kuliner khusus yang membuat orang akrab, misalnya mosomo (bakar sagu).
Dalam kegiatan ini, diajak orang-orang nakal dan suka buat onar. Bila terajak oleh seperti itu, maka keonaran bisa diminimalisir.
Sementara Tjatjo Tuan Saichu, daerah topotara, montunu (bakar), guna memotivasi acara montunu tersebut dibuatlah kebun jagung. Bila panen, maka bersama-sama montunu dale (bakar jagung), sehingga terjadilah keakraban satu dan lainnya.
Kegiatan lain adalah nosidondo (kerja bakti), sepotong hari membersihkan kebun warga, lalu dilanjut dengan acara nontunu (bakar jagung), moteba (bergotong royong) membuat rumah warga.
“Kemudian pertandingan lainnya seperti notilako (engrang). Kegiatan melibatkan banyak orang inilah yang membuat orang akrab, merasa bersaudara, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air,” katanya.
Selain lomba, kata dia, ada juga kearifan lokal dalam bentuk ungkapan, peribahasa, dan pepatah.
Ungkapan yang dimaksud, apabila disampaikan, maka bisa mengubah perilaku seseorang.
“Prinsip dasar berkaitan dengan perilaku manusia. Kalau dalam agama dikaitkan dengan akhlak,” katanya.
Dia menambahkan, ada orang yang memiliki perilaku suka bawa-bawa cerita, di mana dalam ungkapan Kaili dikatakan iko hi no palo ruambolo (orang tidak bisa dipercaya).
“Orang-orang seperti ini dihindari karena berpotensi menimbulkan konflik. Bisa menyebabkan perkelahian,” katanya.
Kata dia, ada juga orang yang suka membual, sehingga menyebabkan terjadinya suatu kericuhan. Biasanya ditegur dengan ungkapkan dalam bahasa Kaili “ane leria love yakumo hi love, bo tano ia aga ngaboro.”
Terpisah, Dosen Fisip Untad, Muhamad Marzuki, mengatakan, masyarakat Kaili dalam bermusyawarah selalu setara.
“Dulu kita punya baruga (tempat musyawarah). Semua orang duduk bersila dan melantai. Tapi sekarang sudah ada kelas, kepala desa dan perangkatnya duduk di atas panggung, masyarakat biasa duduk melantai di bawah. Inikan ada suasana struktural, padahal masyarakat kita lebih fungsional,” katanya.
Dia mencontohkan, adat orang Kaili sangat menjunjung tinggi orang lain. Bila ada orang datang bertamu, dan lauk yang ada hanya telur, maka tuan rumah lebih utama menyajikannya kepada tamu tersebut.
“Bahkan sampai orang tersebut kemudian merasa diterima menjadi bagian dari komunitas sosialnya,” terangnya.
Hal itu, kata dia, akan mendorong munculnya kohesi sosial.
“Kenapa muncul disintegrasi, ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial yang kemudian menjadi radikalisme, karena ketika orang merasa disingkirkan, terabaikan, tidak dipedulikan, maka dia akan mencari ruang-ruang dimana dia bisa eksis,” ujarnya.
Dia menambahkan, agar bisa menciptakan masyarakat yang inklusif, maka tokoh masyarakat (Toma) , tokoh adat (Toda) , tokoh agama (Toga), dan tenaga pendidik harus dilibatkan.
Menurut Marzuki, pewarisan sistem nilai adat harus ditransformasikan kepada anak-anak. Sekarang ini, kata dia, tradisi itu mulai terkikis, hampir dikatakan hilang dalam masyarakat.
“Jadi pewarisan nilai adat di masyarakat harus ditumbuhkan, sehingga tidak ada orang merasa terpencil di masyarkat. Terpencil itu karena dia merasa berbeda, sementara pengaruh-pengaruh yang lain telah masuk pada dia,” katanya.
Bila sudah demikian, lanjut dia, maka Tonda Talusi adalah benteng untuk menangkal dari godaan radikalisme.
Sementara itu, Dekan FKIP, Universitas Tadulako (Untad), Dr Lukman, mengatakan, penguatan budaya atau sosialisasi terhadap pesan-pesan lokal harus diperkuat, seperti kebersamaan, saling menghormati, dan kegotongroyongan, sehingga kecenderungan pada kelompok tertentu yang bergerak secara cepat, bisa terdeteksi dan dieliminir.
“Orang tua dulu punya pesan dan tradisi. Hal seperti ini harusnya lebih banyak dimasukkan pada kurikulum pendidikan agar orang tahu bahwa pada dasarnya budaya kita adalah budaya cinta damai, bukan budaya saling melemahkan dan menghancurkan,” terangnya.
Sebenarnya kata Dosen Antopolog Untad itu, teroris lebih bersifat reaksi terhadap realitas yang ada, serta adanya kesenjangan dan merasa tidak diperdulikan.
”Hal-hal seperti inilah yang perlu disentuh. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa tidak tersentuh secara sosial dan ekonomi sehingga terjadi komunikasi yang tidak berjalan secara baik,” tambahnya.
Makanya, kata dia, apa yang digagas MUI yakni PMB dan PSB, bisa menjadi salah satu upaya membangun kekuatan menangkal perilaku-perilaku yang cenderung keras.
Selain itu kata dia, tindakan keras aparat juga salah satu penyebabnya, dimana tidak memberikan ruang pada orang berperilaku, sehingga membuat tidak nyaman.
“Yang mengancam eksistensi negara, tidak bisa dibiarkan berkembang. Harus ada upaya konkrit yang dilakukan,” katanya.
Sementara Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT), Muzakir Tawil, mengatakan, guna menimalisir radikalisme dan terorismen, lembaga yang dipimpinya menggunakan pendekatan soft aproch.
Pendekatan sosial dan humanis melalui lima kegiatan, di antaranya pendidikan dakwah dan agama, pemuda dan wanita, sosial, budaya dan hukum.
”Terutama kepada budaya lokal. Karena kearifan lokal itu ternyata dapat membekukan, bisa membantu menangkal paham radikalisme dan terorisme. Seperti yang saat ini dikembangkan di Kota Palu dengan semboyan Nosarara Nosabatutu (satu rasa, satu tempat),” tutupnya. (IKRAM)













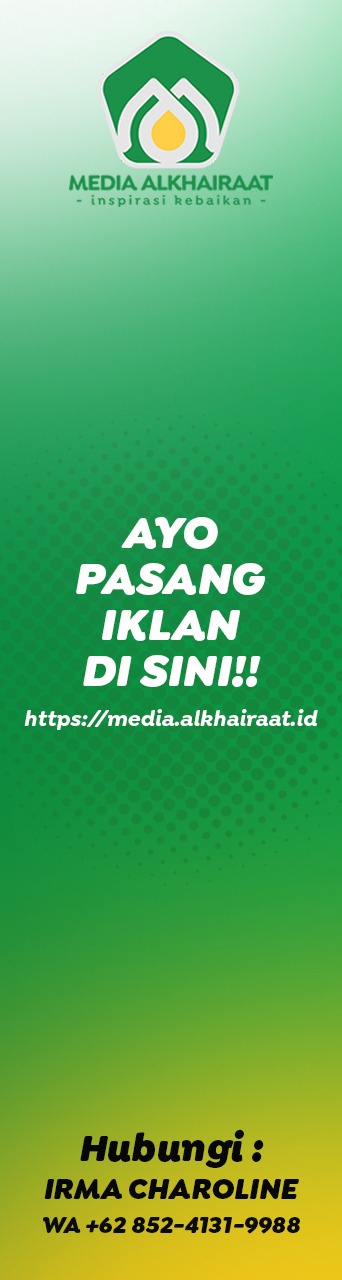
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.