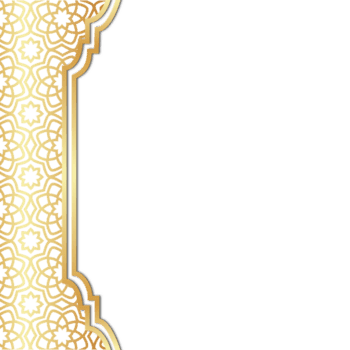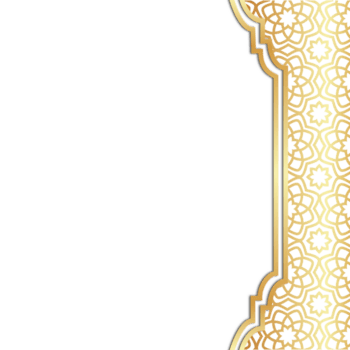Sarung Donggala memiliki banyak kisah menarik. Tak pernah habis jika dituturkan penduduk tempat pengrajin menenun secara turun-temurun.
Tenun Donggala dikenal dengan sebutan lokal buya sabe memiliki kisah di balik pembuatannya walaupun awalnya sarung ditenun tidak berbahan sutra, melainkan hanya menggunakan bahan kapas.
Beberapa narasumber di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, menyebutkan bahwa masyarakat penenun menggunakan kapas hasil budidaya warga setempat. Setelah adanya pengaruh bangsa luar, barulah beralih ke benang sutra.
Adapun penggunaan sutra setelah adanya hubungan dagang dengan bangsa-bangsa luar seperti China, Gujarat (India) dan Arab.
Kisah itu diungkapkan dalam buku yang ditulis William Vaughan; The Narrative of Capiten David Woodard terbitan tahun 1804. Kesaksian David Woodard tahun 1793-1795 itu secara jelas mengungkapkan bahwa masa itu penduduk Donggala telah memiliki keterampilan memproduksi pakaian secara massal, sekaligus menggunakan produksi dari India yang diperdagangkan melalui pelabuhan.
David Woodard menyebut, di Donggala ada penggunaan kain berukuran panjang semacam kain sekatan yang dinamai Palempore, bermutu tinggi hasil tenun berbahan kapas berwarna-warni dipakai saat pesta pernikahan.
Diceritakan bahwa suatu ketika, kain India itu dibentangkan di pintu gerbang kota seolah-olah untuk menghadang tamu rombongan putra raja bajak laut dari Mindanau yang datang melamar Putri Raja Donggala (tidak disebutkan namanya, hanya disebut Raja Tua).
Sejarawan Donggala, Andi Mas’ulun Lamarauna (1942-2000) dalam beberapa catatannya menyebut, bangsa Gujarat dan Arab itulah yang kemudian mengajarkan modifikasi pada putri-putri bangsawan Kerajaan Banawa ketika mengetahui di kerajaan itu ada keterampilan menenun.
Diperkenalkanlah bagaimana tenunan bisa menggunakan sutera sehingga kelak semakin dikenalnya tenun Donggala dalam bentuk kain maka perdagangan benang sutera mulai masuk ke Donggala.
Namun demikian, tidak serta-merta penggunaan kapas ditinggalkan. Keduanya tetap digunakan membuat sarung.

esaksian penggunaan kapas untuk bahan tenun itu masih didapat oleh nenek Hapsa (100 tahun). Menurutnya, penggunaan kapas di Desa Towale berakhir jelang kemerdekaan. Setelah tidak ada lagi penduduk yang menanam kapas. Padahal sebelumnya produksi kapas sangat melimpah, bahkan seluruh kuda tunggangan dibuatkan pelana berbahan kapas selain dipintal untuk tenun.
“Saya masih mengalami masa pembuatan tenun kain memakai kapas di Towale. Cukup lama saya mengerjakan kapas sampai bersih kita pisah-pisahkan agar bersih kemudian kita pintal untuk jadi benang,” cerita nenek yang sejak puluhan tahun berprofesi sebagai dukun beranak itu.
Hapsa belajar membuat benang kapas dari ibu dan neneknya. Begitu pula gadis-gadis lainnya pada zaman dahulu, umumnya harus diajarkan memintal benang atau membuat kain.
Hapsa sendiri tidak bisa bertenun kain, melainkan hanya membuat benang saja sejak usia 15 tahun.
Pekerjaan itu dilakoni Hapsa sejak masa pemerintahan Jepang hingga kemerdekaan.
“Sejak itu pula kapas tidak ditanam dan semua penenun memakai benang sutera yang dibeli dari toko-toko yang ada di kota Donggala,” kenangnya.
Sarung berbahan benang sutera atau kapas yang ditenun di kawasan pesisir Sulawesi Tengah, khususnya di kawasan pesisir Teluk Palu dan sekitarnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling beradaptasi dan mempengaruhi dengan kebudayaan suku luar Sulawesi Tengah, kemudian berkulturasi dalam kebudayaan Kaili. (JAMRIN AB)*