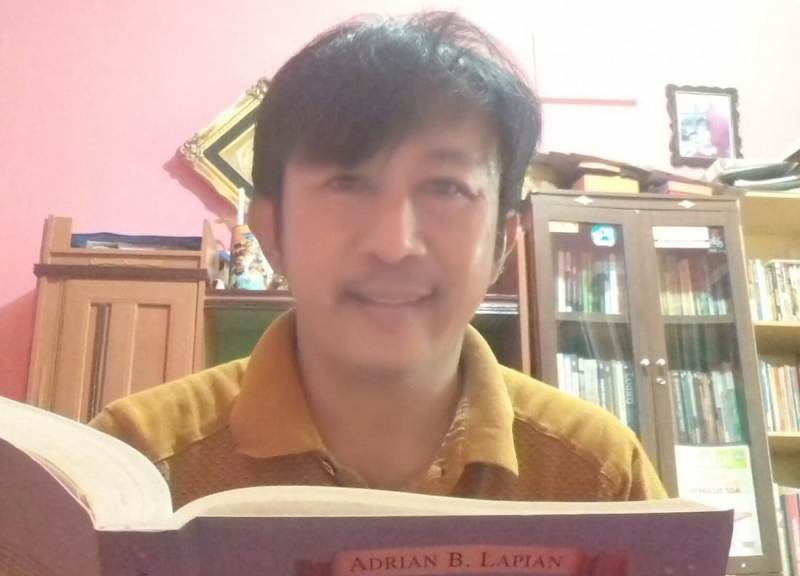OLEH: Jamrin Abubakar*
DUA kalimat di atas pernah familiar dalam percakapan warga kampung di pesisir Pantai Barat, Kecamatan Sojol dan Sojol Utara, Kabupaten Donggala hingga Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. Terutama di kalangan etnis Bugis yang turun temurun bermukim di kawasan pesisir tersebut dan sering melakukan pelayaran ke Pelabuhan Donggala saat masih ramai.
Paddonggalae’ secara harfiah adalah seseorang atau sekelompok orang pergi atau kembali dari kota Donggala dengan pelayaran kapal motor atau perahu layar.
Pelayaran itu dapat dikelompokkan pedagang, nakhoda, ABK (anak buah kapal) atau penumpang. Sedangkan segala aktivitas berkaitan palayaran untuk menjual dan membeli barang (perdagangan) yang dilakukan paddonggalae’ dinamai “maddonggala.”
Pada zamannya barang pesanan atau yang dibeli kemudian dibawa ke kampung asal pedagang menjadi kebanggaan secara kultural memiliki nilai ekonomi tinggi.
Orang yang sebatas mendengar cerita dan hanya mengetahui nama Donggala dari para pelaut dalam imajinasi mereka kota itu begitu penting dengan segala kebutuhan barang produksi modern tersedia.
Sebutan paddonggalae’ dan maddonggala dapat pula dimaknai cara pandang warga dari luar terhadap dinamika perdagangan antarkampung pesisir dengan kota Donggala pada zaman dahulu.
Sejak zaman pemerintahan kerajaan maupun pemerintahan Hindia Belanda hingga tiga dekade setelah kemerdekaan kota ini sangat pesat.
Hampir semua kampung di pesisir Pantai Barat memiliki perahu layar atau kapal motor berukuran sedang melakukan pemuatan kopra dan rotan ke Donggala dan sebaliknya membawa barang-barang produksi untuk diperdagangkan kembali.
Hingga dekade 1980-an pelabuhan masih dipadati perahu motor berkapasitas antara 10 ton hingga 100 ton lebih. Meskipun fungsi utama pelabuhan sudah dialihkan ke Pantoloan, aktivitas bongkar-muat kopra di Donggala masih normal.
Antrian kapal motor dengan muatan kopra berjejeran di area pelabuhan dari tepi muara Sungai Donggala (Tanjung Batu) hingga di sekitar Langgar Arab (Mushallah At-Taqwa) Labuan Bajo.
Aktivitas siang dan malam tak pernah sepi, kapal datang dan pergi untuk bongkar-muat. Ratusan buruh nyaris tidak ada waktu istrahat menyelesaikan pekerjaan. Para ABK lalu-lalang dalam kota mencari keperluan belanja barang, makanan dan berbagai kebutuhan hingga nonton bioskop.
Hingga awal dekade 1990-an masih terdapat tiga gedung bioskop (Mutiara, Muara dan Gelora) memutar film pada siang dan malam dengan penonton kebanyakan para pendatang maupun orang kapal.
Warung makan di dekat pelabuhan hingga di sekitar Pasar Tua (kini lokasinya jadi Bank Sulteng) selalu sibuk melayani pembeli dan toko-toko buka hingga malam hari, pun warung kopi sangat laris.
Kenangan indah itu hanya sebagian di antara warna-warni kehidupan ekonomi kota pelabuhan. Tetapi…pada akhirnya, berangsur-angsur hilang jelang pertengahan dekade 1990-an, satu per satu kapal motor biasa berlayar tidak lagi datang.
Angkutan laut dari Pesisir Barat bagian utara Donggala maupun pesisir selatan (Mamuju atau Pasangkayu) Sulawesi Barat telah tergantikan dengan angkutan darat. Bahkan tidak semua petani dan pengumpul kopra membawa dagangan ke Donggala, melainkan lebih banyak memasarkan ke Kota Palu.
Perdagangan kopra makin menurun, dampaknya sangat dirasakan para ABK dan buruh banyak menganggur. Kecuali di antara pelaut ada yang nekad mengubah rute pelayaran secara ilegal ke Tawau, Malaysia untuk smokel kayu hitam. Kembali membawa bawang putih dan pakaian bekas dikenal dengan sebutan “cakar.”
Sejak itulah aktivitas maddonggala yang dilakukan paddonggalae’ ikut lenyap bersama redupnya perdagangan kopra. Donggala tidak lagi menjadi tujuan utama pedagang komoditi hasil bumi maupun pedagang barang campuran dibawa dari kota tua itu untuk dipasarkan di pesisir Pantai Barat Donggala.
Kini tinggal kenangan dalam memori sebagian warga. Generasi baru lahir pada dekade 1990-an tidak mengalami dan tidak mengetahui. Tidak ada lagi kemeriahan para penyambut perahu di pesisir Pantai Barat Sulawesi Tengah sering mengatakan; “Sudah datang paddonggalae!” Tak ada lagi istilah maddonggala.
Kini tinggal romantisme sebuah kota pernah mengalami kejayaan di masa silam. Nyaris seperti cerita fiksi.
*Penulis adalah Pemerhati Sejarah dan Budaya/Wartawan Senior Media Alkhairaat