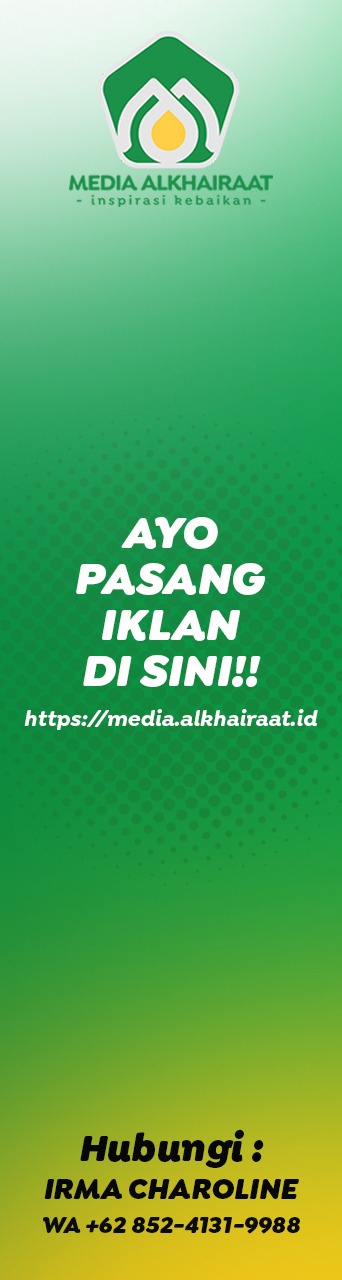OLEH: Amran Tambaru*
Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat (MHA) dan pelaksanaan reforma agraria merupakan dua agenda strategis yang terus diperjuangkan oleh berbagai elemen masyarakat sipil di Sulawesi Tengah.
Dalam konteks ini, tulisan opini berjudul “Kontribusi KARAMHA dan Peran Kampus dalam Perjuangan Pengakuan MHA di Sulteng” yang ditulis oleh Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Tadulako, Dr. Muhammad Hatta R. T., SH. MH, dan dimuat pada media ini tanggal 9 September 2025 lalu, patut diapresiasi sebagai bentuk partisipasi akademik dalam isu-isu strategis tersebut.
Namun, demi menjaga kejujuran narasi dan menghormati kontribusi kolektif para aktor yang terlibat, terdapat beberapa hal yang perlu diklarifikasi.
Tulisan ini dimaksudkan sebagai koreksi atas sejumlah informasi yang tidak akurat, khususnya terkait klaim peran PKBH UNTAD dalam advokasi integrasi hutan adat dan advokasi tanah eks HGU PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi (HHS) di Sigi.
Hal ini penting karena dalam perjuangan panjang seperti ini, kolaborasi dan pengakuan terhadap kontribusi semua pihak adalah kunci.
Integrasi Hutan Adat dalam RTRWP Sulteng
Penetapan Hutan Adat oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2016, termasuk Wana Posangke di Morowali Utara, menjadi tonggak penting bagi gerakan masyarakat sipil.
Pasca itu, Perkumpulan HuMa menggandeng Yayasan Merah Putih Sulawesi Tengah (YMP Sulteng) dan Perkumpulan Bantaya untuk mendorong integrasi hutan adat ke dalam kebijakan tata ruang provinsi.
Pasca itu, HuMa bersama mitranya yakni YMP Sulteng dan Bantaya, berpartisipasi sebagai panelis pada sesi MHA dan HAM di Konferensi III HAM dan Keadilan Eko-Sosial yang digelar oleh SEPAHAM (Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia) di Universitas Tadulako pada 2 Maret 2017.
Diskusi ini menjadi batu loncatan menuju advokasi yang lebih strategis.
Mulai tahun 2018, YMP Sulteng, Bantaya, dan HuMa mulai mendorong integrasi hutan adat ke dalam kebijakan tata ruang provinsi. Audiensi dengan Dinas BMPR Sulteng, konsultasi ke KLHK, Kemen ATR, dan BIG, hingga kampanye media dilakukan secara intensif.
Bahkan, bencana gempa G-28 S pada September 2018 mempercepat urgensi revisi RTRWP Sulteng. Sayangnya, pandemi dan perubahan regulasi pasca UU Cipta Kerja sempat memperlambat proses. Tapi semangat tak padam—kampanye “Hutan Adat sebagai Kawasan Strategis Provinsi” terus digulirkan.
Capaian akhir advokasi ini adalah dengan diakomodirnya Hutan Adat sebagai Kawasan Strategis Provinsi kedalam Perda Provinsi Sulteng No. 1 Tahun 2023 Tentang Revisi RTRWP Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 (Pasal 56). Perda RTRWP ini ditetapkan tanggal 11 Juli 2023.
Klarifikasi atas Klaim PKBH UNTAD
Klaim bahwa PKBH UNTAD dan KARAMHA sejak 2018 telah berhasil memasukkan enam hutan adat ke dalam RTRWP 2023–2042 perlu diluruskan. Faktanya:
- Soal Tahun dan Aktor Utama. Advokasi integrasi hutan adat sejak 2018 bukan dilakukan oleh KARAMHA dan PKBH UNTAD. Faktanya, KARAMHA baru dibentuk pada 10 Oktober 2019 oleh aktivis OMS dan akademisi UNTAD di Kantor YMP Sulteng.
- Kerangka Advokasi. KARAMHA mulai menyusun kerangka kerja advokasi secara sistematis baru pada tahun 2023. Jadi, menyebut bahwa sejak 2018 KARAMHA sudah berperan aktif dalam advokasi tersebut agak melompati kronologi.
- Kontribusi Kolektif. Menyebut sembilan OMS sebagai partisipan KARAMHA tanpa menyebut aktor lain seperti YMP Sulteng, SLPP, BRWA, WALHI, AMAN, Bantaya, HuMa, Ekonesia, dan PUSBANG BAHUSIAT UNTAD, tentu kurang mencerminkan semangat kolaboratif yang selama ini menjadi kekuatan gerakan ini.
Advokasi Tanah Eks HGU PT. HHS: dari Reforma Agraria ke TORA Komunal
Bupati Sigi, Irwan Lapatta, mengambil langkah progresif dengan tidak memperpanjang HGU PT. HHS dan mengalokasikan tanah eks HGU sebagai sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Dari total 362 hektar, ada 160,25 hektar direncanakan untuk pertanian komunal di Desa Pombewe dan Oloboju.
Namun, usulan skema TORA yang diajukan ke Kementerian ATR/BPN justru direspons dengan mekanisme Bank Tanah.
Padahal, dalam audiensi sebelumnya, Menteri ATR/BPN telah menyetujui alokasi langsung untuk pertanian komunal.
Ketegangan meningkat ketika Badan Bank Tanah mengirim surat pemberitahuan pemasangan patok di areal eks HGU, yang ditolak oleh masyarakat dan organisasi rakyat seperti KSP Sangurara dan FKMP.
Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sigi bersama OMS termasuk KARAMHA kemudian menginisiasi pelatihan advokasi dan pemetaan partisipatif atas dukungan Bina Desa serta memfasilitasi Pertemuan Pembangunan Konsensus Ngata Pombewe untuk menyusun rencana pertanian komunal berkelanjutan.
KARAMHA bersama tujuh OMS lainnya—YMP Sulteng, WALHI, BRWA, HuMa, JKPP, Bina Desa, FRAS-ST—didukung oleh PS2KD UNTAD dan PKBH UNTAD, menyusun Kertas Posisi “Bank Tanah Mengorbankan TORA Komunal” yang diserahkan kepada Bupati Sigi dan Pemprov Sulteng serta perwakilan K/L yang hadir dalam forum Seminar dan Dialog Multipihak.
Namun, klaim bahwa PKBH UNTAD berkontribusi strategis dalam penolakan terhadap Bank Tanah perlu dikritisi.
Narasi tersebut tidak mencerminkan kompleksitas proses advokasi dan kontribusi kolektif, terutama PS2KD UNTAD yang berperan sinifikan dalam perumusan Kertas Posisi maupun penyusunan Rekomendasi Seminar dan Dialog Multipihak.
Refleksi dan Etika Kolaborasi
Kritik ini disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat akademik dan advokasi, sekaligus sebagai ajakan untuk menjaga kejujuran narasi.
Aktivis OMS perlu membangun pendekatan dialektika guna menemukan kebenaran substantif.
Klaim sepihak atas capaian advokasi, apalagi di ruang publik, harus dikoreksi agar tidak menyesatkan dan merusak kepercayaan publik.
Nilai-nilai seperti keterbukaan, akuntabilitas, egalitarianisme, dan integritas harus menjadi fondasi kolaborasi antar aktor OMS.
Sudah saatnya KARAMHA dan para aktivis mulai mendokumentasikan pembelajaran advokasi pengakuan hak MHA—baik integrasi hutan adat dalam RTRWP, pengorganisasian TORA Komunal maupun advokasi Ranperda PPMHA—dalam bentuk buku atau media publikasi lainnya.
Karena pada akhirnya, perjuangan ini bukan tentang siapa yang paling berperan, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama menjaga ruang hidup, ruang budaya, dan ruang keadilan bagi masyarakat adat dan petani di Sulawesi Tengah.
*Penulis adalah Koordinator KARAMHA dan Presidium Dewan Kehutanan Nasional 2022-2027