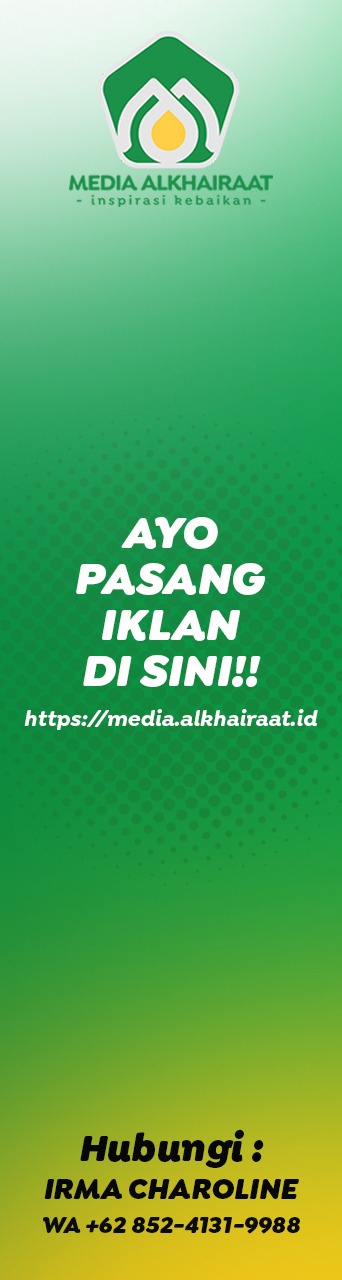OLEH: Muhammad Yunus Kasim*
2 November 2020 menjadi tonggak sejarah, tepat lima tahun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada , janji besar deregulasi dan percepatan investasi kini menghadapi ujian dalam hal pemerataan kesejahteraan.
Undang-undang yang lahir dari semangat penyederhanaan birokrasi ini diharapkan menjadi game changer bagi perekonomian nasional, mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing global.
Namun perjalanan implementasinya tidak selalu mulus. Sejak awal, UU Cipta Kerja menuai kontroversi karena proses pembahasannya yang minim partisipasi publik dan dianggap lebih berpihak pada kepentingan korporasi.
Kini, setelah lima tahun berjalan, berbagai indikator ekonomi memberi ruang untuk menilai secara objektif: apakah deregulasi besar-besaran ini benar-benar berhasil menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
Pertumbuhan dan Investasi: Fondasi yang Mulai Menguat
Dari sisi makro, capaian investasi patut diapresiasi. Kementerian Investasi/BKPM (2025) mencatat realisasi investasi tahun 2024 mencapai Rp1.714,2 triliun, naik 20,8% dari tahun sebelumnya dan melampaui target RPJMN.
BPS (2025) melaporkan tri wulan II pertumbuhan ekonomi 5,12% (y-on-y), dengan tambahan 1,25 juta lapangan kerja baru.
World Bank (2024) menyebut UU Cipta Kerja membantu menurunkan hambatan investasi hingga 10% melalui sistem perizinan Online Single Submission (OSS) yang lebih efisien.
Secara teoritis, capaian ini sejalan dengan pandangan Keynes (1936) dan Harrod-Domar (1946) bahwa peningkatan investasi dapat memacu pertumbuhan melalui efek pengganda (multiplier effect).
Namun, teori tersebut juga menekankan pentingnya arah investasi pada sektor produktif dan padat karya agar manfaatnya lebih merata.
Aspek Tata Kelola dan Kebijakan Publik
Dalam praktik kebijakan publik, UU Cipta Kerja memang mengedepankan efisiensi, tetapi sering terjebak pada pendekatan administratif semata, bukan pada penguatan kelembagaan.
Padahal, Osborne & Gaebler (1992) dalam Reinventing Government menegaskan bahwa deregulasi tanpa tata kelola adaptif hanya akan melahirkan birokrasi ramping di atas ketidakadilan sosial.
Namun efisiensi di tingkat pusat belum sepenuhnya menular ke daerah, di mana koordinasi dan harmonisasi kebijakan masih lemah.
Banyak pemerintah daerah belum menyelaraskan peraturan lokal dengan semangat UU ini, menimbulkan dualisme kebijakan dan ketidakpastian hukum.
Selain itu, partisipasi publik dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan masih terbatas, memperkuat indikasi regulatory capture sebagaimana dikemukakan Stigler (1971), di mana kepentingan bisnis besar lebih dominan dibanding aspirasi buruh dan UMKM.
Anomali di Sektor UMKM, Keuangan, dan Ketenagakerjaan
Sektor UMKM, yang menyumbang 60% PDB dan 97% lapangan kerja nasional (KemenkopUKM, 2025), justru mengalami tekanan struktural.
Deregulasi dan kemudahan izin cenderung lebih menguntungkan perusahaan besar dan investor asing. Banyak pelaku UMKM kesulitan menyesuaikan diri dengan standar administrasi OSS dan kebijakan turunan yang kompleks.
Survei Bank Indonesia (2024) menunjukkan 52% UMKM masih menghadapi kendala akses pembiayaan meski ada program KUR.
Di sisi lain, OJK (2025) mencatat penyaluran kredit investasi mencapai Rp1.435 triliun, namun mayoritas mengalir ke industri besar dan infrastruktur.
Ini memperkuat teori financial intermediation dari Schumpeter (1911) bahwa tanpa kebijakan afirmatif, lembaga keuangan cenderung menyalurkan modal ke sektor padat modal, bukan padat karya.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memang turun dari 5,83% (2021) menjadi 4,76% (2025), tetapi 58% tenaga kerja masih berada di sektor informal. Upah riil buruh stagnan bahkan turun 2,3% setelah disesuaikan inflasi.
Fleksibilitas kerja melalui PKWT yang diperpanjang justru menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja.
Fenomena ini menggambarkan “jobless growth”, di mana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti peningkatan kualitas kerja.
Menurut Becker (1964), kesejahteraan bergantung pada kualitas tenaga kerja, bukan sekadar jumlah lapangan kerja.
Penutup: Membangun Keadilan dalam Pertumbuhan
Lima tahun perjalanan UU Cipta Kerja memberi pelajaran penting: reformasi regulasi tidak boleh berhenti pada deregulasi, tetapi harus menjamin keadilan sosial.
Pemerintah perlu meninjau ulang pasal-pasal ketenagakerjaan yang melemahkan perlindungan pekerja, memperkuat ekosistem keuangan inklusif bagi UMKM, serta memastikan distribusi manfaat investasi lebih merata.
Keberhasilan UU ini tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau pertumbuhan PDB, tetapi dari sejauh mana kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat di akar rumput.
UU Cipta Kerja seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan (empowerment), bukan sekadar deregulasi ekonomi. Dengan cara itu, Indonesia dapat tumbuh cepat, adil, dan berkelanjutan.
*Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako