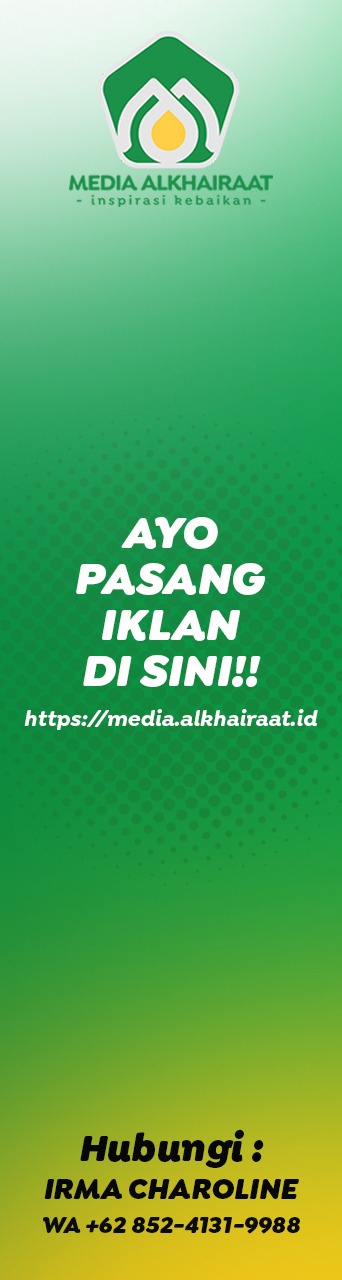OLEH: Dr. Muhammad Hatta R. T., SH. MH*
Perjuangan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, mengalami perubahan paradigma dari hukum positivis menuju hukum inklusif yang progresif, responsif dan partisipatif.
Hukum inklusif merupakan paradigma yang beranjak dari hukum positivis yang kaku menuju sistem hukum yang lebih responsif dan partisipatif, khususnya bagi kelompok marginal seperti Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Paradigma ini menempatkan pengakuan terhadap pluralisme hukum dan partisipasi aktif sebagai pilar utama dalam pencapaian keadilan substantif.
Hukum inklusif menekankan integrasi norma adat dalam sistem hukum nasional dan penghormatan atas hak-hak tradisional yang melekat secara turun-temurun, sebagai manifestasi pengakuan martabat dan identitas kolektif.
Dalam konteks Indonesia dan secara khusus Sulawesi Tengah, hukum inklusif mewajibkan negara untuk memberikan ruang partisipasi MHA dalam perencanaan, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya alam terutama hutan adat yang merupakan basis identitas sosial dan ekonomi masyarakat adat.
Landasan yuridis utama terdapat pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945, yang secara eksplisit mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012).
Dalam kerangka hukum inklusif, proses advokasi pengakuan hutan adat sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Sulawesi Tengah dipandang sebagai terobosan implementatif yang menyatukan kepentingan hukum adat dengan kebijakan tata ruang wilayah.
Hal ini menjadi langkah konkret menyelaraskan aspirasi MHA dengan kebijakan daerah sehingga hutan adat tidak sekedar ada secara sosial-kultural, tetapi juga mendapat status hukum yang melindungi dan melegitimasi eksistensinya.
Pengakuan hutan adat sebagai KSP membuktikan keberhasilan implementasi hukum inklusif dalam penataan ruang wilayah yang memperhatikan aspek sosial budaya dan keberlanjutan ekologis.
Integrasi hutan adat dalam RTRW 2023-2042 memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan kawasan, dan mencegah klaim sepihak oleh pihak lain yang berpotensi merugikan MHA. Ini juga merupakan langkah preventif yang berlaku terhadap konflik agraria dan eksklusi sosial yang kerap terjadi akibat ketidakharmonisan regulasi dan kewenangan yang kabur antara lembaga pusat dan daerah.
Meski RTRWP telah menetapkan hutan adat sebagai KSP, tantangan utama yang masih harus dihadapi adalah fragmentasi regulasi yang sering kali melemahkan perlindungan hukum terhadap MHA. Misalnya, UU Cipta Kerja yang memusatkan kewenangan dalam penataan agraria dan tata ruang nasional dapat bertentangan dengan UU Pemerintahan Daerah serta semangat pengakuan hak adat.
Ketidakselarasan ini menimbulkan ambiguitas hukum yang berdampak pada ketidakpastian perlindungan hutan adat dan tanah masyarakat adat, seperti yang terjadi pada kasus sengketa TORA di Kabupaten Sigi.
Kerangka hukum inklusif menuntut harmonisasi regulasi yang menjamin pengakuan hak-hak tradisional tidak dikerdilkan melalui kebijakan sentralistik, dan sebaliknya memperkuat pemberdayaan daerah dan MHA sebagai aktor utama dalam pengelolaan wilayah adat.
Advokasi pengakuan hutan adat dalam RTRWP Sulteng yang dipelopori oleh KARAMHA yang terdiri dari sembilan organisasi masyarakat sipil, yakni Yayasan Merah Putih (YMP) Sulteng, Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Sulteng, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulteng, dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulteng.
Selanjutnya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulteng, Perkumpulan Bantaya, Perkumpulan HuMa Indonesia, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), serta peran kampus melalui Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako (Untad).
Hal ini mencerminkan komitmen kolektif terhadap inklusivitas hukum, serta menghadirkan contoh ideal perjuangan hukum inklusif di Indonesia.
Sejak 2018, melalui strategi berlapis meliputi advokasi kebijakan berbasis bukti, dialog multi-level, dan mobilisasi publik, koalisi ini berhasil mendorong DPRD dan pemerintah provinsi mengakomodasi enam hutan adat seluas 17.501 hektar sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
Enam hutan adat yang diakui sebagai KSP adalah Wana Posangke (Morowali Utara), Marena, Huakaa Topo Ada To Masewo, Moa, Suaka Katuwua To Lindu, dan Ngata Toro (Kabupaten Sigi).
Pengakuan ini tidak hanya memberikan status hukum yang mengikat, tetapi juga mengukuhkan hak-hak sosial budaya masyarakat adat serta memberikan dasar perlindungan wilayah adat dari intervensi sepihak pihak ketiga atau korporasi.
Dampak Sosial dan Ekologis
Pengakuan hutan adat sebagai KSP di RTRWP Sulawesi Tengah memberikan dampak langsung yang positif bagi kelangsungan hidup masyarakat adat, pelestarian budaya, dan ekosistem hutan.
Kepastian hukum membantu mengatasi konflik agraria yang selama ini menjadi hambatan utama pada progres reforma agraria dan penataan wilayah yang adil.
Perlindungan hutan adat juga menjaga kelestarian sumber daya alam yang menjadi basis ekonomi dan kultural masyarakat adat.
Selain aspek perlindungan sosial dan budaya, integrasi ini mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menjamin kelestarian lingkungan dan penyediaan ekosistem yang sehat sebagai bagian integral dari kebijakan tata ruang yang inklusif.
Tantangan utama terkait pengakuan KSP adalah potensi benturan dengan program dan kebijakan nasional seperti Badan Bank Tanah (BBT) yang dalam beberapa kasus menguasai wilayah TORA yang seharusnya menjadi hak komunal masyarakat adat, sehingga menimbulkan sengketa dan mengancam keberlanjutan pengakuan tersebut.
Selain itu, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan KSP masih terbatas sehingga memerlukan pendampingan teknis dan penguatan sumber daya manusia agar implementasi perencanaan dan pengelolaan wilayah dapat berjalan efektif.
Kontribusi KARAMHA Sulteng Sebagai Income Generating (Immateriil)
Koalisi Advokasi Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat (KARAMHA) bersama Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) LPPM Universitas Tadulako (Untad) berkontribusi strategis dalam advokasi kebijakan pembangunan keadilan substantif berbasis kearifan lokal dan moralitas, mendorong pengakuan hutan adat dalam Perda RTRWP Sulteng 2023-2042 serta menolak Badan Bank Tanah (BBT) yang menghambat TORA komunal.
Kampus lewat PKBH menjadikan perjuangan ini sebagai income generating immateriil dengan meningkatkan reputasi, jejaring, dan pengembangan SDM untuk keadilan sosial dan keberlanjutan. Hukum inklusif menempatkan partisipasi aktif kelompok marginal, seperti MHA dan masyarakat rentan lainnya dalam proses hukum sehingga menghasilkan keadilan substantif.
Landasan konstitusional utama mencakup Pasal 18B dan Pasal 28I UUD 1945, serta Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat bukan hutan negara.
Paradigma ini menuntut pengakuan terhadap pluralisme hukum yang menghargai norma adat dan kearifan lokal guna mencegah eksklusi sosial. KARAMHA dan PKBH menggunakan pendekatan partisipatif, mengintegrasikan norma adat dan hukum positif dalam advokasi RTRWP dengan pendekatan bottom-up yang berbeda dari model top-down klasik.
KARAMHA menggerakkan advokasi kebijakan berbasis bukti, mobilisasi dialog dan publik, sukses mendorong pencantuman hutan adat seluas 17.501 ha dalam Perda RTRWP serta menolak BBT yang melemahkan hak komunal masyarakat.
PKBH Untad memberikan pendampingan hukum pro-bono, riset akademik, serta edukasi hukum bagi MHA, sekaligus memperkuat legitimasi akademik dalam advokasi.
Sinergi ini membangun public trust dan menghasilkan income immateriil berupa reputasi, jejaring kolaborasi nasional-internasional, dan pengembangan SDM berbasis pengalaman lapangan, memperkuat posisi Untad dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Advokasi yang dilakukan oleh KARAMHA dengan dukungan kuat dari PKBH LPPM Untad, sejak 2018, berhasil memasukkan enam hutan adat dengan luas total 17.501 hektar sebagai Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Tengah dalam Perda RTRWP 2023-2042.
Area KSP ini mencakup Wana Posangke (Morowali Utara), dan lima hutan adat di Kabupaten Sigi termasuk Marena, Masewo, Moa, Suaka Katuwua To Lindu, dan Ngata Toro.
Pencapaian ini memberikan dampak besar bagi keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. Status KSP memperkuat perlindungan terhadap hutan adat dengan memberikan dasar hukum yang jelas, menempatkan pengelolaan kawasan tersebut pada prioritas pemerintah provinsi dan mencegah klaim sepihak pihak luar.
Hal ini mendukung kelangsungan kultural dan sosial ekonomi masyarakat adat, serta menjaga ekosistem sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Namun, ancaman tetap ada, seperti aktivitas Badan Bank Tanah (BBT) di Kabupaten Sigi yang mencoba mengklaim lahan TORA masyarakat adat dengan Hak Pengelolaan (HPL), yang berpotensi menimbulkan konflik dan melemahkan hak.
Selain itu, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat adat untuk mengelola dan mengawasi wilayah KSP masih perlu diperkuat agar implementasi kebijakan dapat optimal.
Selain itu, PKBH turut menginisiasi dan mendukung penyusunan naskah akademik dan Raperda tahun 2025, ini tidak terlepas dari peran multi-pihak.
Selain pemerintah, DPRD, dan organisasi masyarakat sipil seperti KARAMHA, kontribusi akademis dari perguruan tinggi, khususnya PKBH LPPM Untad, memiliki peran strategis yang esensial dan multidimensi.
Kontribusi ini bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga substantif dan etis, yang mewujudkan kolaborasi antara teori hukum dan praksis di lapangan.
Pertama, peran sentral sebagai Tim Pengkaji bersama KARAMHA dan Mitra Pemerintah Berdasarkan dokumen, NA & Raperda ini disusun oleh tim pengkaji yang melibatkan akademisi.
Dalam konteks ini, PKBH LPPM Untad, sebagai pusat studi hukum yang berafiliasi dengan universitas terbesar di Palu, menjadi mitra kunci bagi Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulawesi Tengah.
Peran mereka mencakup:
- Riset Yuridis-Normatif dan Kajian Akademis: PKBH LPPM Untad berkontribusi dalam menganalisis secara mendalam landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Perda. Mereka melakukan kajian kritis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, termasuk konflik norma antara regulasi sektoral dan kekosongan hukum di tingkat provinsi. Hasil riset ini menjadi dasar argumentatif yang kuat bagi Raperda.
- Penyusunan Naskah Akademik Partisipatif: Sebagai Tim Pengkaji, akademisi dari PKBH LPPM Untad tidak hanya merumuskan materi secara teoritis, tetapi juga mengintegrasikan data lapangan yang diperoleh dari studi empiris. Mereka menggunakan pendekatan multi-disiplin, yang mencakup studi literatur, wawancara mendalam dengan tokoh adat, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak terkait. Ini memastikan bahwa Naskah Akademik yang dihasilkan mencerminkan realitas sosial di lapangan, bukan sekadar kajian normatif semata.
- Penguatan Kapasitas dan Diseminasi Pengetahuan: PKBH LPPM Untad berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan pemahaman birokrasi dan publik tentang isu MHA. Melalui seminar, lokakarya, dan FGD, mereka membantu menjembatani kesenjangan pemahaman antara hukum adat dan hukum negara.
Kedua, Peran Advokasi dan Pendampingan Komunitas. Selain kontribusi akademis, peran PKBH LPPM Untad tidak dapat dipisahkan dari fungsi pengabdian masyarakatnya. Fungsi ini menempatkan mereka sebagai aktor advokasi yang berpihak pada MHA:
- Advokasi Kebijakan Berbasis Data: PKBH LPPM Untad mengolah data empiris dan riset lapangan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang kuat. Mereka menyoroti persoalan-persoalan spesifik, seperti tumpang tindih wilayah adat dan lambatnya proses pengakuan, yang kemudian diakomodasi dalam rumusan Raperda.
- Pendampingan Hukum Bagi Komunitas: PKBH LPPM Untad, melalui fungsi bantuan hukumnya, memberikan pendampingan hukum langsung kepada MHA yang menghadapi konflik agraria dan kriminalisasi, seperti kasus kriminalisasi MHA To Vatutela. Pengalaman ini memberikan wawasan praktis yang sangat berharga dalam merumuskan mekanisme perlindungan dan pemulihan hak dalam Raperda.
Demikan pula penyusunan kertas posisi untuk mengadvokasi kebijakan publik agar lebih inklusif dan berorientasi keadilan sosial.
Melalui peran ini, PKBH mengukuhkan status UNTAD sebagai knowledge hub dan public justice vehicle yang menegakkan keadilan untuk kelompok rentan.
Peran ini juga memberikan income generating (immateriil) bagi Untad melalui peningkatan reputasi sebagai institusi yang berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan, memperluas jaringan kolaborasi nasional dan internasional, serta menghasilkan pengembangan SDM yang berkompeten melalui pengalaman lapangan.
Pendampingan PKBH di berbagai komunitas adat menjadi contoh nyata bagaimana kampus dapat menjadi aktor penting dalam transformasi sosial dan hukum inklusif.
Strategi Advokasi KARAMHA, Kondisi Empiris dan Tantangan di Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah memiliki 79 wilayah adat dengan total luas hampir 897 ribu ha, di mana komunitas seperti Tau Taa Wana, Ngata Toro, dan Lindu bergantung pada hutan adat sebagai identitas dan sumber penghidupan.
Meskipun pencantuman hutan adat di RTRWP berhasil dilakukan, konflik agraria tetap terjadi, terutama di Kabupaten Sigi terkait tumpang tindih penguasaan lahan antara masyarakat dan Badan Bank Tanah yang memberi Hak Pengelolaan di atas tanah yang diharapkan menjadi TORA komunal.
Fragmentasi regulasi, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan ancaman pengambilalihan tanah menjadi tantangan utama yang harus dihadapi dalam jangka panjang.
Sejak 2018, KARAMHA yang terdiri dari sembilan organisasi masyarakat sipil menjalankan tiga jalur strategis: advokasi kebijakan berbasis bukti, mobilisasi hukum dan dialog multi-level, serta penggalangan dukungan publik melalui audiensi DPRD, dialog teknis, dan petisi anti-BBT.
Strategi ini berhasil membangun public trust yang memperkuat pengakuan MHA di tingkat kebijakan daerah.
Rekomendasi Kebijakan dan Roadmap 2025-2045
Pengembangan roadmap 20 tahun meliputi:
- Fase Konsolidasi (2025-2029): Verifikasi wilayah adat, harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan dengan target Perda Pengakuan MHA.
- Fase Penguatan (2029-2035): Integrasi wilayah adat ke dalam RTRW dan pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal dengan target ≥50% wilayah adat terintegrasi.
- Fase Pemantapan (2035-2040): Optimalisasi pengelolaan hutan adat dan penyelesaian konflik tenurial.
- Fase Keberlanjutan (2040-2045): Evaluasi dan advokasi kebijakan nasional dengan target ≥80% wilayah adat diakui.
Rekomendasi khusus termasuk penghentian aktivitas BBT yang tumpang tindih dengan TORA, pelatihan pluralisme hukum bagi pemerintah dan aparatur peradilan, serta pembangunan sistem pendataan partisipatif yang melibatkan MHA.
Kajian Perbandingan Internasional
Model pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kanada (duty to consult), Korea Selatan (pengakuan norma adat dalam KUHP), Australia (Native Title Act 1993), India (Scheduled Tribes Act 2006), dan landasan internasional ICCPR Pasal 27 memberi pelajaran penting.
Pendekatan yang menekankan konsultasi aktif, pengakuan norma adat dalam hukum nasional, mekanisme verifikasi kepemilikan adat lewat proses peradilan, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, dan perlindungan hak minoritas budaya dapat dijadikan referensi dalam memperkuat kebijakan pengakuan MHA di Sulawesi Tengah.
Kesimpulan
Eksistensi KARAMHA dan peran PKBH Untad secara sinergis mewujudkan paradigm hukum inklusif dengan menjadikan pengakuan dan perlindungan MHA sebagai income generating immateriil yang memperkuat legitimasi kampus dan membangun public trust.
Keberhasilan pencantuman hutan adat dalam RTRWP Sulteng adalah terobosan nasional yang harus diikuti dengan harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan.
Roadmap 2025-2045 menjadi peta jalan strategis untuk memastikan pada Hari Masyarakat Adat Sedunia 2045, pengakuan hak MHA bukan lagi perjuangan, melainkan kenyataan yang dinikmati.
Rekonstruksi dan kajian kritis terhadap Naskah Akademik Raperda PPMHA di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menegaskan bahwa instrumen hukum ini memiliki urgensi yang tak terbantahkan.
Dengan mengadopsi perspektif hukum inklusi, Raperda ini dapat bertransformasi dari sebuah dokumen formal menjadi sebuah alat perubahan yang substantif, yang mampu mengisi kekosongan hukum, mengatasi kesenjangan struktural, dan memberikan perlindungan nyata bagi MHA.
Kontribusi akademis dari PKBH LPPM Untad, melalui riset, pendampingan, dan advokasi, menjadi pilar penting yang memastikan bahwa Raperda ini tidak hanya memenuhi amanat normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.
Keberhasilan Raperda ini bergantung pada komitmen pemerintah daerah untuk tidak hanya mengesahkan Ranperda, tetapi juga mengimplementasikannya secara konsisten, transparan, dan partisipatif, demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menghormati keberagaman budaya.
*Penulis adalah Kapus KBH LPPM Universitas Tadulako