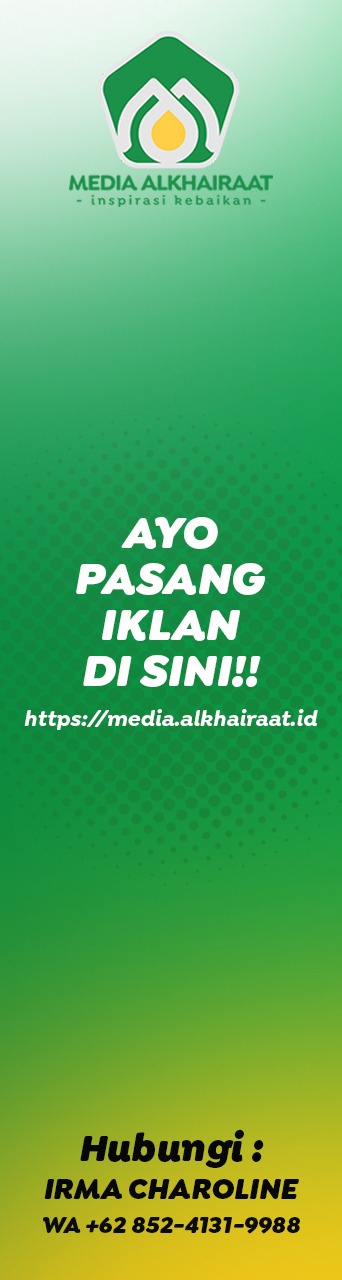OLEH: Efendi Kindangen*
Suatu pagi di Tatura, seorang ibu pekerja harian bercerita bahwa ongkos ojek dari rumah ke pasar kini menghabiskan hampir separuh penghasilannya.
Ia tidak punya pilihan lain sejak Bus Trans Palu berhenti beroperasi. Dalam kalimat sederhana itu, sesungguhnya tersimpan cerita besar tentang keadilan ruang dan hak dasar untuk bergerak.
Kota Palu kini berada pada fase yang kami sebut sebagai “Titik Nol Mobilitas.” Kota ini pernah memiliki sistem bus publik, namun kini seluruh armada berhenti beroperasi. Yang tersisa hanyalah deru kendaraan pribadi dan barisan ojek daring di sepanjang jalan utama.
Di permukaan, masyarakat tampak masih bisa bergerak; namun di bawahnya, ada kerugian sosial dan ekonomi yang jauh lebih dalam.
Kemiskinan Transportasi di Kota yang Tumbuh
Ketika transportasi publik hilang, yang paling dulu menanggung akibatnya bukanlah mereka yang memiliki mobil, tetapi mereka yang hanya memiliki niat untuk bekerja.
Buruh, pedagang kecil, pelajar—semuanya kini membayar lebih mahal hanya untuk berpindah tempat.
Riset kami menunjukkan, sebagian warga Palu kini mengalokasikan 30–50 persen pendapatan bulanannya hanya untuk transportasi pribadi.
Fenomena ini dikenal sebagai transport poverty—kemiskinan yang lahir karena terbatasnya pilihan mobilitas.
Akibatnya, bukan hanya ekonomi keluarga yang terbebani, tapi juga kesempatan sosial ikut menyempit. Banyak pelajar memilih sekolah yang lebih dekat, bukan karena minat, melainkan karena ongkos.
Di sinilah kita memahami bahwa mobilitas bukan sekadar urusan kendaraan, tetapi tentang keadilan akses terhadap kehidupan.
Keadilan Ruang yang Terabaikan
Struktur Kota Palu unik: kota kecil dengan sabuk aktivitas memanjang sekitar 10–12 kilometer. Di barat ada Tipo, di sisi timur–tenggara Kavatuna dan Nupu Bomba, dan di utara–timur laut Pantoloan Boya, kawasan pelabuhan dan perdagangan.
Semua terhubung ke pusat aktivitas di Tatura–Talise, jantung ekonomi dan pemerintahan.
Namun tanpa sistem angkutan umum, wilayah-wilayah ini menjadi terisolasi. Palu seperti terbelah antara zona inti yang ramai dan pinggiran yang jauh.
Ruang kota yang seharusnya menyatukan warga justru menciptakan jurang baru: jurang akses, jurang waktu, dan jurang kesempatan.
Dalam pandangan Islam, ketidakadilan ruang ini bertentangan dengan prinsip maslahah ‘ammah—kemaslahatan umum.
Ruang publik, jalan raya, dan layanan mobilitas adalah amanah bersama, bukan hak eksklusif bagi yang mampu membeli kendaraan pribadi.
Ketika Kota Menjadi Car-Centric
Dominasi kendaraan pribadi telah membawa Palu ke arah yang tidak sehat. Setiap tahun, kemacetan meningkat, biaya BBM melonjak, dan ruang publik menyusut.
Trotoar menjadi tempat parkir, taman berubah menjadi lintasan cepat. Kota ini secara perlahan kehilangan wajahnya sebagai ruang hidup manusia.
Di sisi lain, anggaran publik tersedot untuk memperlebar jalan, bukan untuk memperluas keadilan mobilitas.
Padahal, sebagaimana pendidikan dan kesehatan, transportasi publik seharusnya diperlakukan sebagai pelayanan sosial dasar yang dijamin negara.
Belajar dari Bogor dan Banyuwangi
Kota Bogor memberi pelajaran penting: mereka berani menerapkan sistem “Buy the Service (BTS)”—pemerintah membayar operator bus berdasarkan jarak tempuh, bukan jumlah penumpang.
Kebijakan ini memastikan transportasi tetap berjalan meski okupansi rendah. Bahkan, mereka menyediakan bus gratis untuk pelajar.
Keberanian fiskal ini menandai satu hal: bahwa pemerintah hadir bukan untuk menghitung untung, tapi untuk menegakkan keadilan akses.
Banyuwangi, di sisi lain, menunjukkan bagaimana angkutan kota tradisional (lyn) bisa diubah menjadi simbol modernitas.
Melalui standarisasi seragam, argometer, dan integrasi digital, transportasi publik di sana menjadi layanan yang bermartabat, bukan sekadar pilihan terakhir warga kecil.
Kedua kota itu membuktikan bahwa perubahan hanya membutuhkan kemauan politik dan tata kelola yang baik.
Jalan Baru untuk Palu
Dengan skala kotanya yang kecil dan pola permukiman yang linear, Palu tidak membutuhkan sistem BRT besar yang mahal. Yang dibutuhkan adalah sistem “Micro Bus – Feeder Ringkas”, dengan kapasitas 12–20 kursi dan frekuensi tinggi.
Biaya operasionalnya rendah, subsidi fiskalnya ringan, dan mudah menyesuaikan rute bila terjadi perubahan ruang pasca-bencana.
Sistem baru ini juga dapat berfungsi ganda: selain menghubungkan warga ke pusat kota, ia bisa menjadi bagian dari infrastruktur mitigasi bencana, menghubungkan kawasan relokasi ke zona evakuasi.
Dengan satu langkah, pemerintah bisa menghidupkan kembali mobilitas sekaligus memperkuat ketangguhan kota.
Dari Bus hingga Bursa: Gerak yang Adil
Transportasi publik adalah urat nadi ekonomi rakyat. Ketika bus berhenti, roda kehidupan ikut melambat. Keadilan mobilitas bukan hanya soal efisiensi, tetapi soal martabat warga.
Membangun kembali sistem transportasi Palu berarti mengembalikan hak setiap warga untuk bergerak—untuk bekerja, belajar, dan beribadah tanpa terbebani ongkos dan jarak.
Sebagaimana ajaran Islam menegaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi juga dari kelapangan langkah manusia, maka sudah saatnya kita mengembalikan mobilitas sebagai bagian dari keadilan sosial.
Kota yang adil bukanlah yang jalanannya paling lebar, melainkan yang memastikan setiap warganya dapat melangkah tanpa rasa tertinggal.
*Kalam Insight – Seri Riset Sosial dan Kebijakan Publik Palu