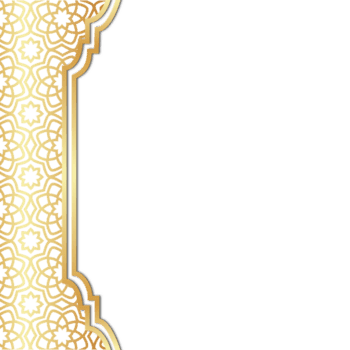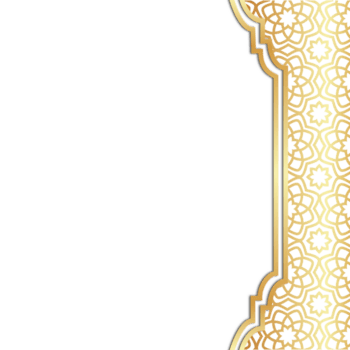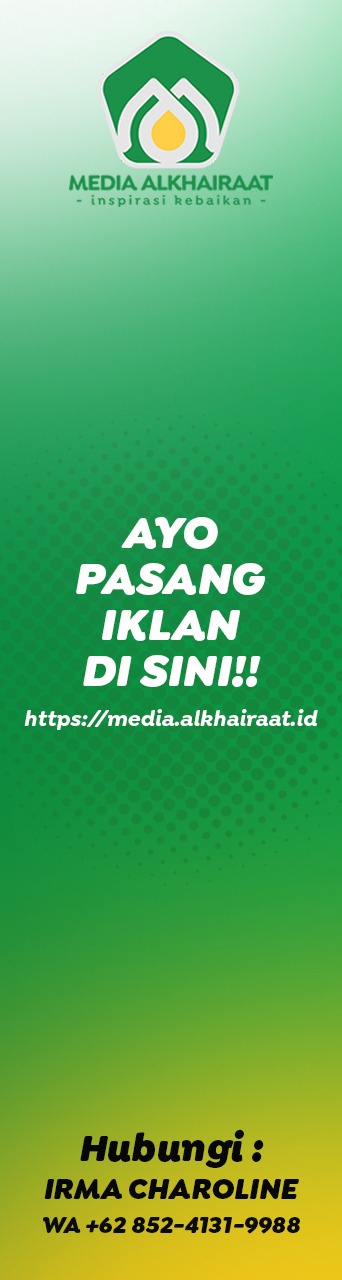Oleh : Firmansyah S.E (Ketua DPW PARTAI PRIMA SULTENG)
24 SEPTEMBER adalah momentum penting untuk merefleksikan sejauh mana negara hadir mendorong kesejahteraan petani di Indonesia. Delapan puluh tahun sejak merdeka, corak ekonomi kita nyatanya tidak banyak berubah dari masa kolonial, masih berorientasi pada penjualan bahan mentah, sementara nilai tambah justru dinikmati korporasi besar dan negara industri.
Dalam konteks ini, Dewan Pimpinan Wilayah Partai rakyat adil makmur ( DPW PRIMA ) Sulawesi Tengah menilai bahwa hilirisasi pertanian adalah langkah maju yang harus ditempuh. Petani tidak boleh terus ditempatkan sekadar sebagai penghasil bahan baku, melainkan sebagai soko guru kedaulatan pangan Indonesia. Hilirisasi akan memastikan hasil panen tidak hanya dijual mentah, tetapi bisa diolah menjadi produk bernilai tambah yang dikuasai oleh rakyat sendiri.
Namun kenyataannya, mayoritas petani di Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah, masih bekerja dengan alat produksi sederhana. Keterbatasan modal membuat proses penggarapan, perawatan, hingga panen tidak optimal. Imbasnya, kualitas dan kuantitas hasil rendah, sementara penghasilan tetap kecil. Situasi ini diperburuk oleh ketergantungan petani pada tengkulak atau koperasi bermodal besar dengan bunga mencekik. Akibatnya, petani terjebak dalam lingkaran utang yang menggerogoti hasil kerja mereka.
Di tengah situasi itu, Koperasi Desa Merah Putih menjadi terobosan yang membuktikan bahwa ada jalan keluar. Dengan koperasi, petani bisa mengakses modal tanpa bunga mencekik, sekaligus memperoleh jaminan pasar hasil panen. Inilah model ekonomi rakyat yang nyata, yang bisa memutus mata rantai tengkulak dan membuka jalan menuju kesejahteraan petani.
Tetapi koperasi saja tidak cukup. Negara wajib hadir dengan intervensi serius: penyediaan tanah, modal murah, teknologi pertanian modern berbasis kolektif, dan jaminan pasar. Tanpa langkah-langkah itu, petani akan terus menjadi korban dalam sistem ekonomi yang eksploitatif.
Krisis lahan pertanian menjadi bukti paling nyata. Secara nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2003 Indonesia memiliki sekitar 8,1 juta hektar sawah. Dua dekade kemudian, pada 2023, jumlah itu tinggal 7,4 juta hektar. Artinya, hampir 700 ribu hektar sawah hilang karena alih fungsi menjadi kawasan industri, pertambangan, hingga perumahan.
Di Sulawesi Tengah, gambaran yang sama terlihat jelas. Tahun 2023 provinsi ini masih memiliki 191.607 hektar lahan sawah. Namun pada 2025, luasannya menyusut drastis menjadi hanya sekitar 185 ribu hektar. Dalam dua tahun saja, lebih dari 6 ribu hektar sawah hilang—setara ribuan keluarga petani kehilangan sumber penghidupan. Penyusutan ini bukan sekadar angka statistik, tetapi tragedi sosial-ekonomi yang mengancam masa depan pangan daerah.
Sebagian besar lahan yang hilang dialihfungsikan menjadi perkebunan besar, kawasan tambang, atau pembangunan infrastruktur. Narasi pembangunan yang diagung-agungkan justru sering mengorbankan petani, yang dipaksa keluar dari tanahnya sendiri. Ironisnya, mereka yang masih bertahan harus menghadapi biaya produksi tinggi, harga pupuk mahal, harga gabah rendah, dan akses pasar yang dikontrol oleh tengkulak. Tidak heran bila pertanian dianggap tidak menjanjikan, sehingga generasi muda enggan melanjutkan tradisi bertani.
Masalah ini sejatinya bukan sekadar soal berkurangnya lahan, tetapi juga menyangkut kedaulatan pangan dan masa depan bangsa. Bagaimana kita bisa bicara swasembada pangan bila sawah terus berkurang? Bagaimana petani bisa keluar dari kubangan kemiskinan bila tanah yang menjadi sumber hidupnya dirampas oleh kepentingan modal besar? Sulawesi Tengah kini berada di persimpangan sejarah: melanjutkan model pembangunan ekstraktif yang meminggirkan petani, atau berani membangun basis kesejahteraan dari pertanian rakyat.
Solusi atas persoalan ini memang tidak sederhana, tetapi bukan pula mustahil. Ada langkah-langkah nyata yang harus ditempuh negara:
- Reforma agraria sejati – Redistribusi tanah bagi petani kecil dan generasi muda yang mau bertani, dengan mengambil alih tanah terlantar, tanah yang dikuasai berlebihan oleh korporasi, serta penyelesaian konflik tenurial.
- Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan – Pemerintah daerah wajib memperketat izin alih fungsi sawah produktif agar tidak mudah dikonversi.
- Subsidi input produksi – Pupuk, benih, dan teknologi pertanian harus tersedia dengan harga murah dan kualitas terjamin.
- Kedaulatan harga dan pasar – Negara harus hadir dalam penetapan harga gabah dan hasil panen, bukan menyerah pada mekanisme pasar yang dikuasai tengkulak.
- Penguatan koperasi dan organisasi petani – Petani harus dihimpun dalam wadah kolektif agar lebih kuat dalam akses modal, pasar, sekaligus memperjuangkan hak politiknya.
Dengan langkah-langkah tersebut, kita bisa menyelamatkan petani dari jurang kemiskinan sekaligus meletakkan dasar bagi masa depan pangan yang berdaulat. Sulawesi Tengah memiliki tanah subur dan tradisi agraris yang kuat. Tetapi tanpa keberanian politik untuk menempatkan petani sebagai pusat pembangunan, semua itu akan hilang ditelan sejarah.