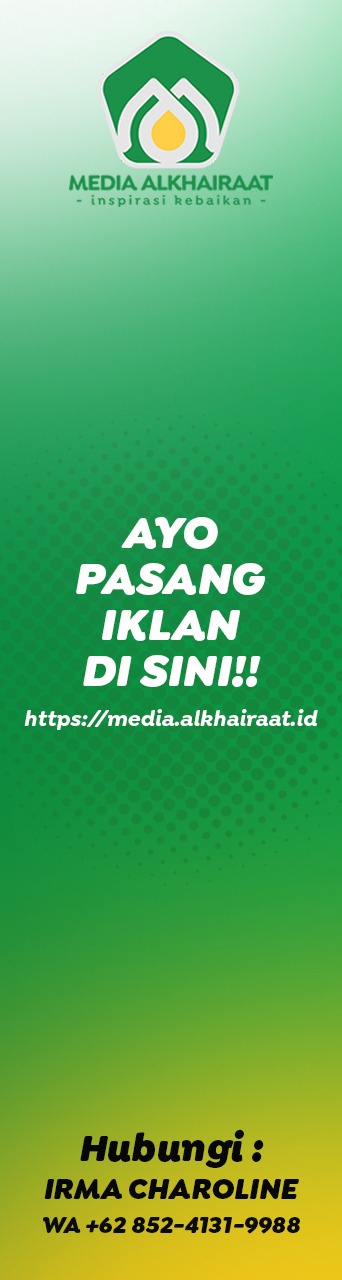Oleh: Viky Eka Indrajaya
Turut prihatin, masyarakat kita kian terdegradasi. Bukan karena kurang nasi tapi karena sering mispersepsi. Informasi ditelan mentah tanpa konfirmasi dan verifikasi. Tidak sadar pemikirannya sudah penuh sampah yang sulit ditanggulangi. Saling tuduh, caci maki dan ujaran benci tak bisa dihindari. Menurut Kemkominfo, pada tahun 2016 tidak kurang dari 800.000 situs penyebar disinformasi. Lebih mengejutkan, terdapat 2.105 isu hoaks terkait pandemi. Upaya pemerintah untuk memerangi patut diapresiasi. Sejatinya hoaks memang tidak bisa ditoleransi. Keberadannya mematikan akal sehat juga hati nurani. Yang membuat saya heran, hoaks juga menyerang para akademisi. Titel tinggi ternyata tidak menjadi garansi. Sekeliling saya tidak sedikit sarjana yang logiknya seakan terhenti.
Penyebaran hoaks ditopang oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangannya memang memiliki dua sisi. Disatu sisi diperoleh beragam manfaat salah satunya memudahkan silaturahmi. Sisi yang lain perkembangan hoaks menjadi tidak terbendung lagi. Pengembangan sarana komunikasi negeri dilakukan tanpa henti. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait banyaknya desa/kelurahan yang memiliki internet di kantor desanya bisa menjadi bukti. Tahun 2018 hanya 38.646 desa/kelurahan menjadi 47.705 desa/kelurahan di tahun 2020 memiliki fasilitas mumpuni. Indikator lainnya juga serasi. Yakni banyaknya desa dengan penerimaan sinyal telepon seluler dengan jaringan kuat dalam negeri. Dibandingkan tahun 2018, tahun 2020 mengalami peningkatan yang tinggi. Awalnya 28.054 desa/kelurahan ditingkatkan menjadi 34.595 desa/kelurahan oleh Bapak Jokowi.
Peningkatan ini memudahkan masyarakat mengakses isu terkini. Bermodalkan gadget di tangan semua menjadi tahu apa yang sedang terjadi. Budaya sharing juga sudah melekat di ibu jari. Permasalahannya sharing dilakukan tanpa dikaji. Alhasil banyak orang malah teracuni. Bukan bertambah pintar, justru makin tidak memahami. Bukan makin peduli, justru menjadi antipati. Bukan menjadi saling menyayangi, justru menjadi saling memusuhi. Mari instropeksi diri. Siapa yang menjadi biang keladi? Mari kita instropeksi, seberapa besar orang merugi? Mari kita instropeksi, seberapa banyak orang akhirnya mati? Saya jawab dengan ironi. Yang salah adalah ibu jari.
Media sosial (medsos) kini tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Bahkan, medsos menjadi tempat terfavorit virus ini bereproduksi. Tercatat 5.502 konten hoaks tentang covid-19 menyebar melalui medsos terkini. Instagram, facebook, twitter, kemudian apa lagi? Tambahan referensi, pengguna internet di Indonesia menyentuh angka 63 jeti. 95 persen dari jumlah tersebut mengakses internet untuk bermain sosmed hingga petang dari pagi. Saya sedikit dilema apakah hal-hal berikut merupakan prestasi? Ketika Indonesia menjadi peringkat keempat dunia pengakses Facebook sehari-hari. Yang ada, justru hal tersebut membuat saya semakin ngeri. Ibaratkan berenang di lautan, masyarakat Indonesia terjun ke medsos tanpa ada kemampuan diri. Bukannya memperoleh ikan, malah hanyut kesana sini.
Menghadapi hoaks, senjata paling ampuh adalah literasi. Dengannya akan bisa dilakukan proses filtrasi. Menyaring kotoran hingga tersisa sesuatu yang murni. Akan menyehatkan bila dikonsumsi. Literasi negeri perlu diperbaiki. Hasil survei di tahun 2019 oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan Indonesia merupakan 10 negara terbawah dalam hal literasi.
Mari kita jangan berdiam diri. Jangan menunjuk orang kemudian merasa berpuas diri. Justru diri sendirilah yang seharusnya terlebih dahulu dikoreksi. Meningkatkan literasi wajib dijalani. Memperbanyak bacaan bisa menjadi solusi. Tidak hanya membaca tetapi juga memahami. Agar proses membaca yang efektif bisa diperoleh nanti. Dengan hal tersebut harapannya hoaks di Indonesia dengan sendirinya akan mati.
*Penulis adalah ASN di Lingkungan BPS Kabupaten Buol