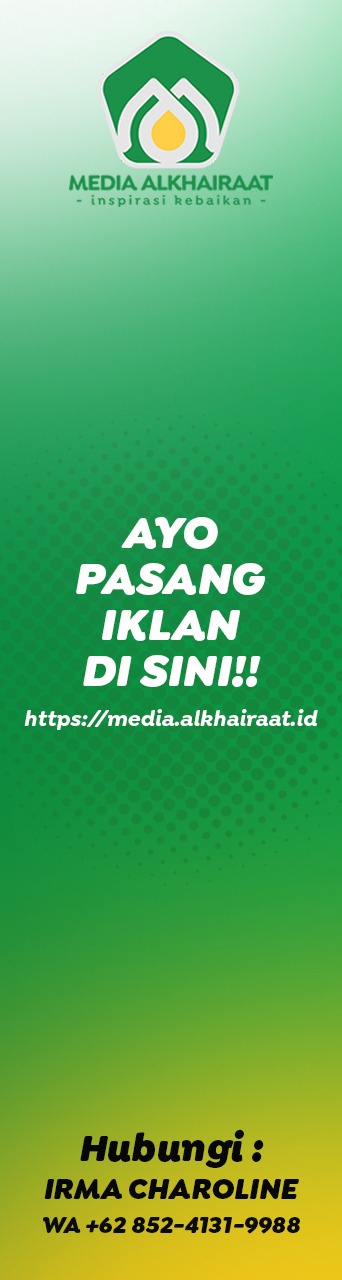OLEH: Lukman Khakim. SST*
Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar di dunia. Sebuah negara dikatakan sebagai negara agraris jika mampu menghasilkan produk pertanian dalam skala yang besar. Akan tetapi, terdapat indikasi sektor pertanian lambat laun mulai tidak diminati.
Menurut data BPS, persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor pertanian menurun setiap tahunnya.
Pada tahun 1986 persentasenya mencapai 54,36 persen. Angka tersebut menurun secara konsisten setiap tahunnya hingga pada Februari 2022 hanya sebesar 29,96 persen.
Hasil Sensus Pertanian 2013 yang dilakukan BPS senada dengan fakta di atas. Jumlah rumah tangga pertanian pada tahun 2003 sebesar 31,23 juta. Alih-alih bertambah, angka tersebut malah berkurang menjadi 26,13 juta rumah tangga di tahun 2013. Kemungkinan besar angka tersebut akan berkurang kembali pada Sensus Pertanian tahun 2023 mendatang.
Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia juga cenderung melemah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000, sektor pertanian menyumbang 15,60 persen PDB Indonesia. Angka tersebut bergerak fluktuatif dengan tren menurun hingga pada tahun 2021 menjadi hanya sebesar 13,28 persen.
Penurunan jumlah petani di Indonesia mengindikasikan berkurangnya minat masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian. Masalahnya jika dirinci berdasarkan umur, pengurangan petani lebih banyak terjadi pada usia muda (di bawah 45 tahun), sementara persentase petani dengan umur 55 ke atas justru meningkat.
Hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan terdapat 39,21 persen rumah tangga pertanian dengan petani utama berumur kurang dari 45 tahun (usia muda). Pada tahun 2018 angka tersebut turun menjadi 35,80 persen (SUTAS 2018). Sementara itu dari sensus dan survei yang sama, persentase rumah tangga pertanian dengan petani utama berumur 55 tahun ke atas (usia tua) justru bertambah, dari 32,76 persen di tahun 2013 menjadi 35,97 persen di tahun 2018.
Berkurangnya petani muda dan dominannya petani tua menunjukkan kurangnya regenerasi petani karena kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Fenomena ini disebut aging farmer atau penuaan petani.
Fenomena penuaan petani akan berdampak pada proses pembangunan sektor pertanian berkelanjutan, produktivitas pertanian, daya saing pasar, dan jauh dari itu akan mempengaruhi ketahanan pangan suatu bangsa. Fenomena penuaan petani tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun terjadi di berbagai belahan dunia seperti Jepang, Amerika, Thailand, Uni Eropa dan lain-lain.
Berbicara mengenai kesejahteraan petani, sebagian besar petani di Indonesia berada pada kondisi menengah ke bawah. Hal tersebut karena pertanian yang mereka kerjakan merupakan pertanian skala kecil yang tidak terlalu menguntungkan. Sekitar 58 persen rumah tangga petani pengguna lahan di Indonesia pada tahun 2018 merupakan petani gurem, yaitu petani yang mengusahakan lahan seluas kurang dari 0,5 hektar.
Jumlah rumah tangga petani gurem bahkan meningkat dari 14,2 juta rumah tangga di tahun 2013 menjadi 15,8 juta rumah tangga di tahun 2018. Tidak heran jika 55,2 persen penduduk miskin di Indonesia berada di perdesaan, tempat dimana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani.
Apakah fakta bahwa kiprah sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia melemah dari waktu ke waktu cukup menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan sektor pertanian? Jawabannya tentu tidak.
Seperti kita tahu kebutuhan paling mendasar manusia adalah kebutuhan pangan. Sektor pertanian akan selalu menemukan pasarnya. Terlebih, sektor pertanian adalah salah satu sektor dengan resistensi paling tinggi ketika terjadi krisis ekonomi.
Pada kondisi pandemi covid-19 tahun lalu misalnya, ketika hampir seluruh sektor tumbuh negatif, sektor pertanian justru tumbuh positif. Deretan negara pengekspor hasil pertanian terbesar justru diisi oleh negara maju seperti Amerika Serikat, China dan Australia.
Beberapa fakta di atas cukup menjadi alasan bagi Indonesia untuk terus membangun sektor pertanian ke arah yang lebih baik dan menjadikannya salah satu leading sector.
Pembangunan sektor pertanian bisa diawali dari penyediaan data pertanian yang berkualitas. Laju stagnan atau bahkan cenderung turun dari sektor pertanian bisa jadi disebabkan oleh kualitas data yang kurang baik.
Seperti kita tahu, setiap kebijakan harus didasarkan pada fakta dan bukti-bukti ilmiah (evidenced-bassed policy) agar tepat sasaran, tak terkecuali kebijakan di ranah pertanian. Bayangkan jika data yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan tidak sesuai dengan kondisi lapangan, tentu yang terjadi adalah garbage in garbage out, kebijakan tidak tepat sasaran dan tidak berkualitas. Alih-alih memperbaiki keadaan, sektor pertanian malah makin mundur dan makin tidak diminati.
Untuk itu penyediaan data statistik pertanian yang berkualitas bisa menjadi langkah awal pembangunan jangka panjang sektor pertanian.
Penyediaan data statistik pertanian diatur dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pada UU tersebut diatur Badan Pusat Statistik sebagai Badan penyelenggara kegiatan statistik dasar wajib melaksanakan Sensus Pertanian setiap sepuluh tahun sekali.
Namun data sensus saja tidak cukup, Instansi yang berkaitan dengan pertanian juga wajib menyelenggarakan pengumpulan data statistik sektoral.
Pada pelaksanaannya, Kementrian Pertanian dan instansi lain yang berkaitan dengan pertanian bisa dibantu oleh BPS dalam menyelenggarakan statistik sektoral. Terlebih setelah disahkannya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, BPS baik pusat maupun daerah berperan sebagai Pembina Data yang wajib membina instansi-instansi dalam penyelenggaraan satatistik sektoral.
Hal itu bertujuan agar setiap data yang dikumpulkan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia yaitu memeiliki standar data, memiliki metadata, memenuhi interoperabilitas data dan memiliki referensi data.
Sesuai Undang-Undang Statistik, BPS melaksanakan Sensus Pertanian setiap 10 tahun dan dilaksanakan pada tahun yang berakhiran 3. Sensus pertanian pertama kali dilaksanakan pada tahun 1963. Sensus Pertanian berikutnya pada tahun 1973, 1983, 1993, 2003, 2013 dan pada tahun 2023 mendatang.
Sensus pertanian merupakan salah satu agenda besar BPS dalam upaya menyediakan data statistik yang berkualitas. Keberhasilan dari kegiatan yang bertajuk “Mencatat Pertanian Indonesia” tersebut bergantung kepada seluruh elemen yang terlibat, tidak terkecuali seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi responden nantinya. Kejujuran jawaban responden menentukan kualitas data Sensus Pertanian.
Pada bulan ini, tepatnya tanggal 26 September akan diperingati sebagai Hari Statistik Nasional. Tanggal tersebut diambil dari tanggal diundangkannya Undang-Undang Statistik Nomor 7 Tahun 1960. Hari Statistik Nasional menjadi momen yang tepat bagi kita semua untuk merenungi betapa pentingnya data berkualitas bagi pembangunan Indonesia, tidak terkecuali data pertanian.
Tidak lupa, penulis juga mengajak pembaca sekalian untuk menyambut dengan baik Sensus Pertanian 2023 yang akan diselenggarakan tahun depan. Diharapkan dengan data statistik pertanian yang berkualitas, sektor pertanian di Indonesia akan semakin maju dan semakin mengukuhkan Indonesia sebagai negara agraris yang berpengaruh di dunia.
* Penulis adalah ASN di BPS Kabupaten Poso